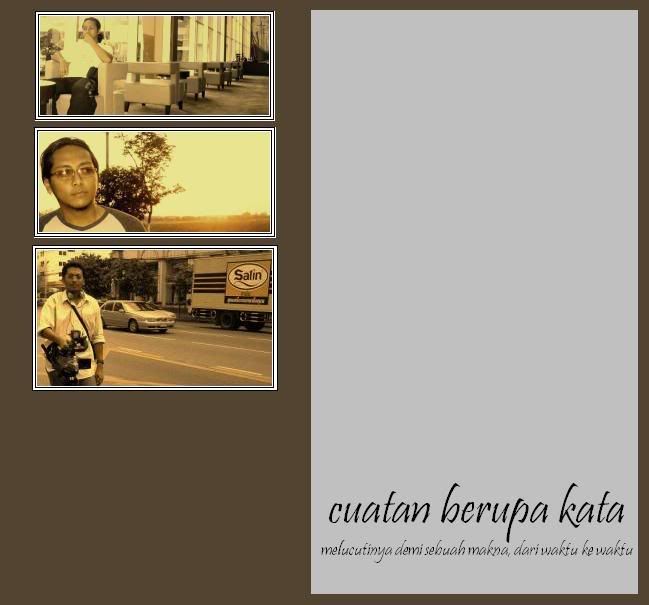Thursday, March 10, 2011
Pagi ini, saya menangkap sebuah pemandangan biasa namun entah kenapa, mengharukan.
Di ujung jalan Wijaya II, sepeda itu melenggang masuk meramaikan jalanan yang relatif masih sepi. Saya ada di ujung lamunan, saat itu, di balik kemudi sahabat mesin saya, Galancy.
Seorang lelaki tua mengayuh sepeda itu perlahan, melintas tepat di depan saya. Seorang anak perempuan duduk manis di belakang lelaki tua itu.
Entah kenapa, saya merasakan ketenangan dalam harmonisasi mereka di atas sepeda. Angin pun seperti bergerak mengiringi tanpa pernah mau menghembus terlampau kuat.
Saya lantas mencoba memahami benak anak perempuan itu.
Asumsi saya begini:
Pagi tadi, dan mungkin juga di pagi-pagi lain sebelumnya, ia pergi ke sekolah dengan diantar oleh bapaknya. Lewat kayuhan sepeda ontel itu, mereka berdua membelah jalanan di selatan Jakarta. Entah dimana rumahnya dan entah dimana pula sekolahnya. Hingga tentu saja, entah berapa lama mereka membuai angin pagi di atas sepeda ontel itu.
Lantas, ketenangan mereka lagi-lagi menggelitik saya dan tak berhenti berputar di rumit labirin otak saya. Ada aura kenikmatan di situ. Aura yang sungguh jauh berbeda dengan aura yang dimiliki oleh para pengendara motor dan mobil yang sebelumnya saya jumpai di sepanjang perjalanan dari rumah hingga sampai di jalan Wijaya II itu – aura tergesa dan tertekan yang bingung dengan ambisi dan kompetisi.
Saya kemudian mencoba mengurai waktu dan memetik beberapa potongan dari masa lalu.
Saya jarang sekali punya momen seperti mereka - diantar ke sekolah oleh Bapak. Setidaknya di masa-masa awal saya berseragam putih merah.
Mungkin karena jarak SD saya tak terlampau jauh dari rumah. Cukup berjalan kaki sekitar 25 menit, maka kaki-kaki kecil saya sudah sampai di ruang kelas.
Saya juga tak perlu diantar karena memang saya sudah punya sobat setia dalam perjalanan setengah panjang itu. Ali.
Atau mungkin juga karena saya laki-laki. Bapak tahu atau sengaja memaksa saya untuk punya kekuatan, keberanian dan kemampuan untuk menjaga diri saya sendiri. Setidaknya dalam perjalanan dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Tak peduli meski usia saya baru 6 tahun.
Atau mungkin juga karena Bapak tak pernah punya alat transportasi sendiri untuk mengantar saya. Tak sebuah sepeda ontel sekalipun. Apalagi motor atau mobil. Bapak lebih suka naik angkot jika harus pergi agak jauh dari rumah, sementara keseharian Bapak kerap disesaki oleh jalan kaki dari rumah menuju kampus tempat ia mengajar – yang juga dekat dari rumah, dan mungkin dengan langkah-langkah besarnya bisa ditempuh dalam waktu 10 menit saja.
Ada rasa cemburu, mungkin.
Prosesi antar ke sekolah itu sepertinya hanya pelatuk saja, karena sejujurnya saya memang jarang punya momen berdua dengan Bapak. Bukan ingin membuat petisi atau protes pada Bapak yang kini sedang terbaring sakit. Saya hanya membayangkan alangkah indahnya jika sempat punya banyak waktu berdua dengan Bapak. Kemana saja, dan untuk melakukan hal apa saja.
Apalagi, tadi pagi hati saya juga berbisik – Kemanapun saya pergi, apapun yang saya mau lakukan, saya tak akan gentar jika ada Bapak yang antar.
Wijaya, 10 Maret 2011.
dhank Ari at 4:38 PM
Monday, January 31, 2011
Romantisme Warteg Saat Ide Mandeg
Seingat saya, warteg atau warung tegal baru masuk ke dalam bagian dari hidup keseharian adalah pada pertengahan tahun 1993.
Masa kecil hingga saya berbaju putih abu memang jarang sekali dilintasi momen makan di restoran atau bahkan warung makan biasa. Makan pagi, siang dan sore itu lebih sering berkutat di ruang tamu rumah atau di pojokan lain di dalam dan luar rumah.
Juga ketika saya sudah mulai pulang lebih lama dari jam sekolah, makan siang atau sesekali makan malam itu biasa dilemparkan pada momen makan di rumah teman.
Mencicipi masakan orang tua atau pembantu mereka.
Nah, ada satu momen yang lucu dimana saya menjatuhkan telur gulai yang masih utuh hingga berguling liar di lantai dingin rumah Ismir saat saya hendak memotong telur itu dengan sendok. Ketika itu, saya masih kelas 4 SD.
Malu?
Luar biasa. Tak terkatakan lagi.
Tapi saya berkeras untuk memakan telur itu. Kuman dan bakteri mungkin saja sudah mati karena tertimpa telur utuh itu. Kalaupun cuma pingsan, rasanya tak sempat mereka bangun melebihi kecepatan sendok dan tangan saya yang bekerjasama mengembalikan telur itu kembali ke atas piring.
Tahun 1993, saya memulai hari-hari buas di tanah rantau. Tak jauh, memang. Hanya sekitar 183 kilometer saja dari rumah Ledeng. Empat setengah hingga 6 jam perjalanan Bis Ekonomi, atau tiga setengah hingga empat setengah jam perjalanan Bis Patas AC. Semuanya masih lewat puncak. Jalan Tol Cipularang mungkin masih belum berbentuk janin sekalipun.
Tahun 1993, saya mulai mengenal warteg di daerah Kukusan Teknik, Depok. Kukusan adalah nama kampungnya. Teknik adalah titel yang dilekatkan karena perkampungan ini letaknya persis di belakang Kampus Teknik Universitas Indonesia.
Bagi saya saat itu, warteg adalah pilihan rumah makan murah yang bisa menjaga kelangsungan keberadaan lembaran-lembaran rupiah dalam dompet eiger palsu dengan motif spiderman saya.
Menunya kadang sama dan membosankan. Tapi keseharian saya saat itu tak menyisakan pilihan, meski banyak orang bijak bilang jika pilihan itu selalu ada.
Tapi, ini bukan omong kosong.
Saat itu memang tak ada pilihan lain.
Jadi, akrablah saya dengan warteg. Mulai dari beberapa warteg jawa hingga warteg Bang Udin yang nyatanya tak bertahan lama, entah karena alasan apa.
Entah kenapa, saya merasa istimewa setiap kali makan di warteg.
Mereka tak pernah protes atau mendelik sinis meski saya hanya memesan nasi setumpuk penuh dan sayur gratisan.
Meski praktis, saya hanya membayar nasi itu saja. Saya bahkan kerap meminta air putih dibungkus kantong plastic untuk dibawa pulang.
Tahun 1995, saya, Hadi dan Haries punya tambahan langganan warteg yang baru. Letaknya ada di ujung simpang jalan margonda dan nusantara, masih di kawasan Depok. Warteg itu kerap kami buru setiap kali kami selesai latihan fitness di satu tempat fitness yang saya sudah lupa namanya.
Saya selalu memesan tambahan nasi. Mungkin karena nafsu makan yang menggila karena tenaga terkuras di alat-alat kebugaran itu. Atau juga mungkin karena aku berpikir untuk tak makan lagi setelah itu hingga tidur menjelang.
Biarlah lapar itu melepaskan rindunya pada bubur atau nasi uduk keesokan paginya.
Tahun demi tahun berlalu. Belasan bahkan puluhan warteg pun saya hampiri. Tetap dengan beberapa ciri khas yang tak pernah pudar.
Tetap dengan kerinduan saya.
Tetap dengan ramainya dinamika pemuasan batin saya.
Ya, pemuasan batin.
Tak bisa dipungkiri, warteg telah banyak membantu.
Membantu menyediakan makan saat keuangan saya terbatas.
Membantu mengenalkan pada banyak teman baru.
Membantu mendinginkan cuaca jiwa yang liar dan panas.
Dan satu lagi, warteg telah membantu menunjukan celah solusi bagi ide kreatif saya yang mandeg.
Seperti yang saya alami, saat masih bekerja di Astro TV.
Saya bukanlah pekerja yang bisa duduk seharian di depan komputer.
Saya lebih senang mengakrabi jalanan. Melodi itu ada di sana. Emosi itu ada di sana.
Namun, lagi-lagi namun, saya selalu ingin mencoba.
Berat, memang.
Ide saya seringkali buntu, seperti mencari hantu.
Saya pun akhirnya sering menyelinap keluar selama setengah hingga 2 jam untuk mampir di Warteg Shanti, tak jauh dari kantor.
Hanya untuk segelas kopi susu atau jeruk hangat dan beberapa batang sigaret.
Hanya untuk menyapa jalanan lagi untuk mengatakan bahwa saya tetap milik jalanan, bukannya milik gedung mewah yang penuh orang berdasi.
Hanya untuk mencari bala bantuan bagi otak yang mandeg.
Dan benar saja.
Otak saya selalu cair setiap kali duduk di bangku panjang dari kayu itu. Meski kadang harus membuat jarum jam penunjuk menit itu melintasi angka yang sama hingga dua kali.
Untungnya, tak pernah ada delikan sinis karena saya duduk terlalu lama dengan hanya memesan satu gelas kopi. Tak pernah ada perilaku penanda pengusiran dari pemilik warteg. Tak pernah ada tanda keberatan, dan malah kerap mengakrabi saya dengan aneka obrolan ringan.
Itulah kenapa saya selalu merasa istimewa setiap kali makan di warteg.
Otak saya tak mandeg.
Perut saya wareg.
Batin saya pun tak eneg.
Hingga aku kerap keluar dengan hati yang ajeg.
Wijaya, 24 Desember 2010.
dhank Ari at 5:10 PM
Bike to Bomb
Entah karena latah atau sekedar ingin beraktifitas lebih sehat, Ahmad bin Abu Ali memilih sepeda untuk melintasi jalan Kalimalang pada suatu pagi yang kembali datang dengan penuh kejutan itu.
Lebih sehat? Mungkin.
Lebih peduli lingkungan? Ah, mungkin juga.
Bukankah kedua alasan itu yang kerap ditempelkan penggiat aktifitas bersepeda di kota besar seperti Jakarta ini pada permukaan ucapan mereka atas tanya-tanya yang sebenarnya tak pernah nyata terlontar?
Bersepeda demi menyelamatkan bumi.
Bersepeda demi menyelamatkan diri.
Saya sendiri sudah menitipkan rupiah pada dua buah sepeda di rumah. Satu untuk saya, dan satu lagi untuk istri saya. Kami juga ingin bersepeda demi menyelamatkan bumi, demi menyelamatkan diri hingga mungkin saja nanti bisa menyelamatkan mobil tua kami dari kelebihan makan bahan bakar.
Nyatanya, berat bersepeda di kota yang hiruk ini.
Berat pula bersepeda di sibuk hari-hari yang mencekik.
Merasa bersalah, sebenarnya, pada bumi, meski tak pernah sempat meminta maaf setiap kali roda empat itu berderu dan memberikan tambahan asap bagi para penyelamat bumi di atas roda dua yang berputar tak sekencang roda dua lain yang jumlahnya makin menggila seperti kelinci.
Jadi, saya seperti ingin bertanya pada Ahmad bin Abu Ali saat ia memilih sepeda pagi itu, “Kenapa roda dua yang kau lajukan pagi itu?”
Latahkah kau, seperti jutaan orang Indonesia lain?
Atau mungkinkah kau rindu pada hadirnya komunitas penanding “Bike to Work”?
Bisa jadi, sepeda memang satu-satunya alat transportasi yang ia punya. Pergi ke pasar, ke rumah teman, ke kantor kelurahan, ke tempat kerja, atau ke ujung manapun di bumi, kau kayuh sepedamu.
Tapi kenapa harus meledak, Ahmad bin Abu Ali?
Saya juga rindu komunitas, tapi saya tak pernah terpikir untuk membuat komunitas “Bike to Bomb”
1 Oktober 2010
dhank Ari at 5:06 AM
Thursday, January 27, 2011
Angka Cantik Yang Tak Lagi LentikSaya suka prosesi isi bensin di hampir seluruh SPBU Pertamina.
Selain karena alasan yang memang menjelma sebagai sebuah keharusan, saya punya alasan lain yang lebih personal.
Yang lebih sensasional.
Saya suka deretan angka cantik yang selalu serupa, yang kerap keluar dari layar indikator volume premium yang berpindah tempat ke tangki mobil saya. Angka-angka cantik yang datang sebagai konversi dari nominal rupiah yang saya cerabut dari dompet atau dari saku celana saya yang makin sempit saja.
Maklum, saya kerap membulatkan nominal rupiah setiap kali isi bensin, hingga angka cantik itu terus keluar dalam rupanya yang berbeda-beda.
Kadang nominal itu adalah 200 ribu rupiah. Kadang 100 ribu rupiah. Kadang juga, 50 ribu rupiah saja jika dompet teramat tipis oleh rupiah yang bisa disisihkan untuk bisa memenuhi isi tangki.
Dengan premium seharga 4500 rupiah di Pertamina, saya suka sekali setiap kali angka-angka digital ataupun angka-angka tradisionil di layar indikator volume itu muncul. Kadang 44,44. Kadang 22,22.
Kadang juga, 11,11.
Angka cantik, saya sebut angka-angka itu.
Angka-angka yang kemudian seperti bulu mata lentik perempuan manis yang mengerling manja ke arah saya.
Angka-angka cantik yang eksotik meski tak pernah dibubuhi lipstik.
Namun, sebulan terakhir ini benar-benar menggelisahkan.
Ada berita buruk, meski masih merupakan perdebatan yang belum menemukan bukti yang valid. Kualitas bahan bakar premium di Pertamina disinyalir memiliki kualitas yang sangat buruk, hingga dapat merusak salah satu suku cadang kendaraan yang biasanya jarang mengalami kerusakan, kecuali oleh usia pemakaian. Satu per satu kasus kerusakan pompa bensin mobil bermunculan (pada umumnya taksi), yang jumlahnya bahkan mencapai hingga sekitar 6000 buah mobil.
Sungguh mengejutkan.
Berita yang kemudian menyeret saya pada sebuah malam, sekitar tiga bulan yang lalu.
Mobil saya mogok di jalanan sepi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Niat untuk bergegas sampai di rumah agar bisa segera melintasi malam dengan lelap, hilang begitu saja. Saya malah harus bersimbah keringat, mulai dari mencari bantuan mobil derek hingga upaya keras mengantarkan mobil itu ke garasi saya yang terbuka.
Oh, my dear sweet galancy!
Usut punya usut, pompa bensin mobil saya rusak. Tak mampu lagi menggenjot bahan bakar dari tangki menuju turbin. Sebagai konsekuensi, saya tipiskan lagi isi dompet untuk membeli pompa bensin baru sambil berpikir keras untuk mencari cara untuk mengisi dompet itu kembali, selain oleh kartu nama dan slip ATM.
Apa mungkin pompa bensin saya juga rusak karena kualitas premium yang buruk?
Saya tidak tahu pasti.
Bisa jadi juga karena faktor usia mobil saya yang memang sudah uzur. Nyaris 16 tahun.
Tapi, saya tak bisa bohong jika saya benar-benar terganggu.
Angka-angka cantik itu pun nyatanya tak lagi menjelma sebagai bulu mata lentik seorang perempuan cantik.
Angka-angka cantik itu kini seperti noda setitik, yang lantas bisa merusak susu sebelanga.
Dan kemarin malam, saya sudah beralih dari Pertamina, dan menjauh dari kesenangan saya memelototi angka-angka cantik itu.
Saya mendapati angka itu berubah menjadi 32,25. Entah angka apa lagi yang akan saya temui nanti, terutama ketika dompet itu juga sedang tipis oleh rupiah.
10 Agustus 2010
dhank Ari at 8:03 AM
Monday, August 09, 2010
Jakarta, 3 Agustus 2010Saya tak pernah ingat apa saya bisa memiliki keistimewaan untuk memilih keringat mana yang layak keluar dari pori kulit saya dan mana yang tidak. Terutama jika menyangkut pada sebuah tujuan yang baik.
Pada sebuah mimpi.
Terutama pada sebuah mimpi.
Mimpi memang kadang harus dibangun dengan berbelok sebentar pada sebuah rimba atau sekedar berhenti di rumah singgah yang bobrok.
Bagi sebagian besar orang, mimpi memang tak langsung berwujud nyata lewat jelajah pada sebuah jalan bebas hambatan atau jalan pintas. Segelintir orang mungkin bisa, tapi tak demikian bagi sebagian besar orang, termasuk saya.
Ada lumpur-lumpur yang harus saya genangi dulu. Lumpur-lumpur yang mungkin enggan dinikmati sebagian orang, terutama yang berharap tetap klimis dan dandy saat sampai di ujung mimpi.
Saya memiliki mimpi besar.
Saya punya gambaran sebuah puncak.
Namun, saya juga punya gambaran beberapa gua dan bukit terjal yang mengelilingi puncak itu.
Belum terlihat jalan pintas. Belum juga terlihat titian rapih dan nyaman yang bisa langsung membawa saya ke puncak. Apalagi lift mewah beralaskan permadani emas. Semua masih terlihat mencengangkan sambil mengira-ngira kemampuan dan senjata yang saya miliki.
Menyerah atau memilih mencari jalan lain atau diam menunggu bala bantuan sambil berkhayal?
Tidak.
Saya hanya tahu bahwa saya harus mencapai puncak itu, dimana pedang mimpi tertancap di sebuah batu besar, menungguiku untuk mencabutnya dan mengarahkannya ke matahari. Seperti tokoh superhero He-Man, yang menjajah sebagian masa kecil saya dengan kisah heroiknya yang kartun.
Makanya, saya siap masuk ke dalam gua atau mendaki bukit yang terjal itu, jika perlu.
Saya sudah menyiapkan keringat. Tak sedikitpun terlintas dalam pikiran saya untuk memilih keringat yang harus keluar dari pori, untuk mencapai puncak.
Saya tak mau manja dan hanya memilih keringat yang sepertinya bisa memberikan kepastian saja.
Hidup ini tak pernah bisa dipastikan.
Saya merasa percuma jika keringat itu hanya disimpan dan disiapkan untuk jalan terjal pilihan saja atau bahkan jalan pintasnya saja. Keringat juga perlu dilatih, bukan? Agar keringat bisa mewarnai hidup saya dan bukannya memberikan halangan bagi mata saya untuk melihat dan kekuyupan yang terlalu.
Saya bukan ngengat, yang kadang memilih keringat mereka.
Saya bukan ngengat, yang demikian antusias mendekati cahaya-cahaya palsu dari lampu yang berpijar tak abadi, hingga mereka lupa pada bunga-bunga malam yang butuh penyerbukan dari mereka.
Saya juga bukan ngengat, yang sering jadi hama petani.
Semoga saya juga tak jadi oportunis yang berpikiran pendek, yang masih memilih keringatnya sendiri untuk didenominasikan dengan nilai tukar uang.
dhank Ari at 7:27 AM
Jakarta, 2 Agustus 2010Saat pertama kali memiliki telepon genggam, saya kerap menatapi layar kecil hitam itu sambil berharap telepon itu berbunyi. Senang rasanya jika ada orang yang rela menyisihkan uangnya dan memutar nomor telepon saya. Apalagi jika panggilan itu dari calon nasabah yang akan memberi saya rezeki lebih di hari itu.
Pulsa masih demikian mahal. Mungkin hanya orang berduit yang bisa seenaknya nelpon sana nelpon sini. Hanya orang yang benar-benar perlu, yang siap menukar apa saja demi sebuah panggilan singkat lewat frekwensi telepon genggam.
Saya sendiri, harus berpikir lebih dari 3 kali sebelum memutuskan untuk melakukan panggilan telepon dari telepon genggam saya. Lebih seringnya, saya pergi ke wartel agar tahu persis jumlah rupiah yang harus saya bayar, bukan mendadak kaget melihat sisa pulsa setiap kali saya memutar nomor *888#.
Beberapa bulan sebelumnya, sebelum saya memiliki telepon genggam, saya juga kerap menanti pesawat pager saya berbunyi.
Lagi-lagi, senang rasanya diperhatikan. Senang rasanya ada yang mencari tahu atau sekedar memberi tahu.
Namun, waktu berganti demikian cepat.
Sejak 3 tahun yang lalu, saya justru mengalami phobia setiap kali mendengar telepon genggam saya berbunyi. Bunyi telepon itu seperti neraka! Memaksa saya untuk meluangkan setitik waktu untuk mengangkat telepon sementara saya ada di tengah kesibukan yang hiruk atau justru sedang ada dalam kesunyian yang memang sengaja saya cari.
Saya seperti tak ingin lagi ponsel saya itu berbunyi. Biarlah sunyi saja dan duduk diam di pojok.
Atau, janganlah berbunyi seperti candu. Cukup sesekali saja. Cukuplah bunyi telepon itu menjadi pemanis harian, bukannya pengisi harian.
Saya lantas sering mengatur mode panggilan di ponsel saya dengan mode “silent”. Biarlah saya tahu mereka memanggil, dan biarlah mereka memanggil dengan kesunyian saja. “Silent Mode” hadir seperti bukan sebagai sebuah paksaan, melainkan permintaan. Selayak kunjungan santun pada agenda harian saya yang kadang seperti bom waktu.
Memang, saya akui, saya jadi sulit dihubungi.
Maklum, saya belum mampu mendengar bunyi yang tak berbunyi. Sementara ponsel yang bergetar pun kadang tak mampu saya deteksi, apalagi karena ponsel itu kerap bersembunyi di balik tumpukan kertas yang ramai di meja kerja.
Mungkin butuh telepati yang kuat untuk bisa menghubungi saya. Seperti menyampaikan sinyal pada bulan untuk kemudian diteruskan pada saya lewat bantuan angin.
Maaf, pada semua kerabat, rekan dan terutama istri saya, bila memang sulit melakukan panggilan yang bisa segera tersambung.
Saya sedang krisis privasi.
Privasi kini seperti makanan basi yang tak bisa lagi disantap.
Privasi kalah oleh tuntutan zaman yang menuntut semua hal yang serba cepat. Termasuk perihal “berhubungan”. Bukan lagi bulan, hari atau bahkan jam, perubahan itu bisa terjadi. Perubahan bisa terjadi dalam hitungan detik. Perubahan yang seringkali harus dikomunikasikan, harus mencapai titik “berhubungan” tadi.
Saya kadang jadi terperangkap dalam kebingungan millenium.
Saking bingungnya, saya seringkali melakukan telepati satu arah. Seperti rekan-rekan kerja saya yang sudah akrab dengan jawaban saya setiap kali ditanya mengenai up-date macam-macam hal.
“Bukannya udah gue bilangin, ya?”
“Kapan, dhank?” atau “Lewat apa?”
“Eh….dalam hati.”
dhank Ari at 7:26 AM
Jakarta, 30 Juli 2010Membuat orang senang itu pahala.
Menumbuhkan tawa di muka yang mengkerut itu juga pahala.
Keseharian memang perlu dicerahkan, perlu dilintaskan cahaya, meski mungkin hanya datang sesekali.
Saya selalu ingin menjadi lelaki itu. Penumbuh tawa. Namun saya tahu persis, saya sendiri kadang sulit menertawakan kebodohan saya sendiri. Padahal, seorang tua pernah bilang bahwa salah satu ciri kedewasaan adalah saat saya bisa menertawakan kesalahan-kesalahan saya sendiri, bukannya mengutuk atau menyudutkan diri di pojokan gelap yang menjerumuskan.
Maklum, tawa seringkali bisa mendinginkan pikiran saya yang panas, meluruskan penyimpangan-penyimpangan jiwa yang sedang sesat dan menegakkan kepala yang terus ingin tertunduk sambil menatap monotonnya aspal atau tanah yang berdebu. Hingga pada akhirnya, saya bisa lebih mudah memusatkan perhatian pada pemikiran yang positif.
Namun, lagi-lagi saya bilang, bahwa saya sulit menjadi lelaki itu. Seringnya, saya hanya membuat banyak lelucon yang tak lucu atau hanya terdiam mematung saat seseorang menantikan kata-kata surga atau sekedar tatapan menenangkan. Yang ada, saya hanya terus mencoba untuk menertawakan kesalahan-kesalahan saya, agar semakin terlatih dan mahir. Alhasil, aura positif saya mungkin tak banyak menular pada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan tawa itu. Pada jiwa-jiwa yang butuh keramaian nuansa yang menyenangkan.
Ah, tak apa. Toh saya memang tak akan berhenti berusaha.
Terutama untuk harmoni yang juga saya nikmati.
Lantas, ada sekelompok perempuan yang suka menyenangkan banyak lelaki.
Atau menyenangkan sekelompok lelaki tertentu, dengan keinginan dan kegemaran yang kurang lebih sama.
Perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang suka menyenangkan banyak lelaki dengan imbalan setumpuk rupiah.
Perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang kerap membawa barang dagangannya kemana-mana. Barang dagangan yang sebenarnya adalah titipan semenjak ia mula dilahirkan. Barang dagangan yang kadang bisa ia nikmati sendiri, terutama ketika menemukan pembeli yang kebetulan mereka suka.
Mereka terus melakukan jual beli, seakan sudah menjadi seorang pegawai pemasaran yang tak perlu sulit mengatur strategi penjualan atau menentukan neraca target dalam buku tebal yang penuh nomor telepon orang-orang tak dikenal namun berpotensi sebagai pembeli.
Biarlah para lelaki itu yang menekan nomor mereka.
Tak seperti tenaga pemasaran kartu kredit yang harus menatap lekat-lekat ribuan angka, sebelum akhirnya ia menekan tuts telepon bergaya Blackberry dan kemudian menandai tanda hitam di samping beberapa angka itu untuk setiap penolakan.
Biarlah para lelaki itu yang menangkap isyarat tersembunyi atau bahkan cukup dengan menunjuk salah satu hidangan dalam menu yang tertulis atau terpampang di meja display.
Inilah para perempuan yang suka menyenangkan para laki-laki.
Para tuan.
Inilah para perempuan yang juga sering membeli nasi pecel ayam dari Pak Jaya, sebelum atau setelah melakukan transaksi jual beli.
Sama seperti saya, malam ini. Membeli nasi pecel ayam dari Pak Jaya, setelah sebelumnya berusaha untuk membuat aura senang di lantai 4 ruko sederhana di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan.
Bedanya, saya tak mencoba menyenangkan orang demi imbalan tumpukan rupiah.
Saya hanya ingin menjadi bagian dari lingkar pertemanan yang kokoh, yang jauh lebih berharga dari sekedar tumpukan rupiah cepat saji.
dhank Ari at 7:26 AM
Jakarta, 29 Juli 2010Orang bilang, hidup itu penuh warna.
Warna apa, De? Merah, Kuning, Kelabu, Hijau Muda atau Biru?
Tapi, tak ada yang meletus, kan, hingga membuat duniamu jadi kurang berwarna?
Orang terus menerus bilang jika hidup itu penuh warna. Tempat saya bekerja dulu bahkan punya slogan “hidup penuh warna”.
Tapi apa sih sebenarnya warna dalam hidup?
Saya dulu paling senang kalau Ibu membelikan Pentel, merek cat air dan juga crayon yang kala itu demikian populer diantara kami, anak sekolah lucu-lucu yang belum mengenal gincu atau sikap-sikap yang rancu. Apalagi ketika Papap buka kursus menggambar bagi anak-anak di kantor IFFH, Pasirkaliki. Setiap hari rabu dan sabtu, crayon atau cat air itu selalu ada di tas kulit saya yang kotak, yang kembar tapi beda warna dengan milik kakak saya, Neng Lia.
Saya gemar mencoretkan warna itu berkali-kali. Pada kertas. Pada buku. Pada sisa kanvas punya Papap. Atau bahkan pada dinding, ketika saya belum bisa berkata “Mama”.
Hampir seluruh batang berwarna itu saya sikat habis hingga kadang hanya menyisakan seujung kecil saja yang sudah sulit untuk saya pegang dengan tangan saya yang masih teramat mungil itu.
Saya telah mewarnai banyak hidup saya kala itu, yang mungkin tercurah lewat gambar rumah, gambar pemandangan, gambar mobil, dan gambar-gambar lainnya yang saya warnai. Mungkin, saya telah mencoba untuk mewarnai hidup saya di usia sedini itu.
Tapi apa benar itu yang kemudian saya sebut mewarnai hidup?
Terutama setelah belakangan, saya lebih memilih untuk menghabiskan crayon atau cat warna hitam dan putih saja, untuk membuat sketsa-sketsa kasar wajah Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, bahkan sampai sketsa wajah-wajah fiktif yang lebih banyak saya temui dalam mimpi.
Apa lantas hidup saya kemudian menjadi ikut hitam putih?
Saya tak ambil pusing kala itu.
Saya hanya menyukai imaji-imaji hitam putih. Saya bahkan sangat menikmati sketsa-sketsa pinsil 6B saya, yang kemudian saya lenturkan garis-garis tegasnya dengan ujung jari saya hingga menghitam ruas-ruasnya, untuk mendapatkan efek bayangan atau juga kilasan.
Sungguh, “hidup penuh warna” tak pernah saya pedulikan.
Sampai akhirnya saya menemukan warna-warna terbaik di ujung senja. Di setiap ujung senja. Di sudut manapun yang pernah saya injak.
Termasuk di sebuah tempat magis bernama Pototano.
Di Pototano, warna senja itu bisa melahirkan jutaan warna dalam hidup saya seperti efek domino. Sama dengan yang pernah saya cumbui juga di banyak sudut terbuka alam, terutama pesisir.
Di Pototano, ruas jiwa saya tak albino. Seluruh pigmen itu terlahir tanpa harus mengenal batasan atau larangan berekspresi. Semuanya datang dan berbincang manis dengan saya, sebelum, saat dan setelah saya menyebrang selat untuk kembali ke Pulau Lombok dari Pulau Sumbawa.
Saya sampai lupa pada sandal saya yang sudah koyak dan tertinggal di bawah bangku ferry itu.
Saya sampai lupa jika pegal dan penat itu pernah demikian menjajah di bawah panas suhu Sumbawa pada hampir selama 20 hari sebelumnya.
dhank Ari at 7:26 AM
Jakarta, 27 Juli 2010Tak semua orang tahan banting.
Masalahnya, saya gak mau mereka jadi sinting.
Saya sendiri kadang ingin lepas dari bantingan itu dan pergi ke pinggir pantai untuk melihat semburat senja perlahan turun menitipkan cerita. Saya ingin berbicara ringan lagi dengan angin, yang selalu setia menemani kemana saja saya pergi.
Lelah saya terbanting, atau dibanting. Atau bahkan sengaja membantingkan diri sendiri, seperti frase yang sudah saya kenal lama sekali, “banting tulang”.
Tapi kadang, kita memang tak punya pilihan banyak, atau tak ada pilihan sama sekali selain membantingkan tulang kita sendiri pada lapisan kenyataan yang demikian keras hingga membuat sumsum tulang itu semakin menipis dan mulai menyemburkan godaan-godaan untuk menjadi sinting.
Saya tak suka melihat gurat keputusasaan yang seakan terus menuliskan kata-kata “lelah dan kesal” ke udara. Saya tak suka melihat nafas yang seakan tak bisa lepas dari hisapan sesak dan berat. Tapi saya kadang kehilangan celah untuk membuat mereka bergerak gembira lagi di atas rel yang memang harus mereka titi dengan langkah-langkah panjang yang mungkin tak sempat berhenti di stasiun-stasiun antara selain satu-satunya stasiun tujuan.
Saya kadang berpikir egois.
Saya kadang ingin membuatkan sampan saja untuk mereka dan menghanyutkannya ke muara untuk bertemu senja. Atau tenggelam saja dan menemukan dunia atlantis yang mungkin tak perlu membuat mereka terjatuh.
Saya kadang berpikir egois.
Saya kadang ingin segera mengundang saja janin-janin baru lagi untuk menjalani ritual banting tulang bersama.
Untuk mengakrabi pedih dan lelah itu.
Untuk tertawa dan memaki bersama.
Namun, itu artinya saya sudah sedikit sinting. Tak semua orang tahan banting, memang. Tapi bukan berarti saya bisa seenaknya menghanyutkan saja mereka hingga keruh sampai muara.
Mungkin saya hanya perlu membuatkan kapal pesiar dan membuatkan peta menuju muara, sambil membekali mereka dengan pundi dan tawa yang cukup.
Lagi-lagi untuk bertemu semburat senja.
Untuk berbicara dengan angin.
Untuk meminta tolong pada angin agar satu waktu nanti mereka akan kembali dengan nyawa yang sudah penuh.
Darimana, kira-kira, leluhur kita mencipta frase “banting tulang”? Apa karena waktu itu hanya orang-orang kurus kelaparan tak berdaging yang akhirnya harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup, sementara para borjuis berkantong tebal, berperut buncit hanya perlu tanda tangan untuk uang cepat saji?
dhank Ari at 7:25 AM
Jakarta, 20 Juli 2010Tanpa diduga, air mata itu perlahan turun.
Bukan dari mata saya, melainkan dari mata seorang teman yang sekonyong pamit untuk pulang lebih awal.
Saya berhenti memutar kaset itu dan menatapnya sekejap.
Beberapa detik sebelumnya, ia pamit.
“Bang, pamit duluan, ya!”
“Oh, ya. Kalau besok gak ada liputan, tolong tulis time code kaset-kaset ini, ya!”
“Iya, Bang. Tapi agak siang, ya. Saya mau ngelawat dulu. Temen saya meninggal.”
Di situlah air mata itu turun.
Setelah tatapan singkat itu, spontan saya bertanya.
“Kenapa? Sakit?”
“Iya, Bang. Lever.”
Ia lantas urung meneruskan niatnya untuk beringsut turun ke lantai dasar, urung menyalakan motornya dan urung pula bergegas menuju rumah sahabatnya yang sudah meninggal itu. Ia kalah oleh air mata yang memaksanya terduduk lesu di tangga kecil menuju lorong sholat. Ia sontak menutup matanya rapat, berusaha untuk menahan laju air mata yang tak mau dibendung, sambil bercerita mengenai sahabatnya yang baru saja meninggal, satu dari empat sekawan yang sudah merenda cerita sejak mereka dipersatukan oleh institusi sekolah bernama SMP.
Tak banyak yang bisa saya katakan. Saya hanya mengajaknya berpikir perlahan dan tenang tentang semuanya. Termasuk kesiapan ia mengendarai motor ke arah Condet dalam suasana hati yang terlampau bimbang seperti itu.
Melihatnya lesu dalam duka membuat saya perlu menahan dia beberapa saat di kantor. Ia seperti tak akan bisa menahan genggaman tangannya di stang motor, mengendalikan injakan rem dan gas bahkan memusatkan pandangannya ke depan, jika gundah itu seperti duri yang sedang mencari titik-titik rawan yang bisa ditusuk hingga berdarah berliter-liter.
Sedikit banyak, saya jadi teringat Fajar, teman saya yang meninggal karena Leukemia di awal tahun 1995.
Air mata juga turun saat itu. Termasuk dari mata saya yang saat itu sedang angkuh dengan kebebasan seorang anak manusia yang seperti baru terlahir karena mulai berpikir di dunia yang nyatanya demikian kikir.
Apalagi saya ingat jika beberapa saat sebelum ia divonis menderita Leukemia, saya pernah bertengkar hebat dengannya. Satu pukulan keras dari tangan saya pernah mendarat di perut kurusnya, yang mungkin sedang bergelut dengan aliran darah yang tak sempurna. Saya menyesal luar biasa atas pukulan itu, juga atas sumpah serapah kekesalan padanya yang keluar sebelum dan setelahnya.
Saya lantas beberapa kali datang ke rumahnya, melihatnya minum susu kuda liar, sambil perlahan melihat rambutnya yang makin menipis. Sesekali saya memperhatikan kesabaran ibunya.
Saat ia meninggal, tak ada pilihan lain selain menangis.
Tak bisa dibendung air mata itu. Termasuk saat saya menuliskan kata-kata ini sekarang.
Air mata hanya berhenti di saat saya merangsek masuk di lingkaran para pelawat pagi itu. Air mata juga tak turun saat saya dan Budi Dosen membuat nisan darurat dengan menuliskan nama sahabat kami itu. Dejavu jika mengingat saya pernah menulis nama itu di catatan absen kelas setiap saat ia gagal masuk ruang kuliah.
Apa kabar kamu, sahabat?
Sudah lebih 15 tahun kamu tak bersama kami lagi. Semoga kamu baik-baik saja di sana.
Doa yang sama saya panjatkan bagi sahabat seorang teman yang meninggal beberapa jam yang lalu.
Dan, semoga kamu pun bisa menuntaskan air mata untuk sahabatmu itu dengan senyuman. Apalagi jika kamu telah berusaha semampumu untuk melepas sahabatmu pergi, untuk bertemu kembali kelak.
Amin.
dhank Ari at 7:25 AM
Jakarta, 7 Juli 2010Ada satu nama yang menyihir saya bertahun-tahun.
Diego Armando Maradona.
Dialah orang pertama yang tidak saya kenal, tapi mampu meyakinkan saya jika sepakbola adalah sesuatu yang sangat indah. Bahwa sepakbola adalah titisan kebahagiaan yang tiada terkira.
Saya pun lantas bermain bola, seperti ingin menyamai Maradona. Dimanapun saya menendang bola, imaji Maradona itu selalu ada di kepala saya. Tak pernah mau lepas. Sampai akhirnya saya pun ingin sekali mengenakan kostum bernomor 10 setiap kali bermain bola.
Inilah dhank Ari, pemain bola debutan dari pemukiman padat Negla, Ledeng.
Gol demi gol saya cetak ke gawang lawan. Mulai dari gol dari bola plastik yang sering bikin merah kaki jika ditendang terlalu keras, bola tenis yang kadang luput ditendang karena terlampau kecil dan lincah, bola bliter (alias bola kulit) yang kadang terasa demikian berat apalagi saat sudah mulai mengempes, bola karet berbagai ukuran yang arah lesatannya kadang melenceng dari jalur dan tak sesuai dengan yang diharapkan, hingga bola-bola kertas yang sengaja saya buat saat bola-bola itu tak terbeli atau hilang atau sedang teronggok rusak di pojokan rumah.
Sesekali kami nakal.
Bola voli atau bola basket kami gunakan juga untuk bermain bola sepak, sebelum akhirnya kami berdiri salah tingkah di ruang guru setelahnya, mendengarkan satu dua petuah yang diselingi sekaan keringat yang terus mengucur di sekujur wajah dan tubuh kami.
Esoknya, kami seringkali lupa dimarahi dan kembali mencari celah mencicipi lagi bola-bola yang dibuat untuk diakrabi tangan, bukannya kaki.
Belakangan, saya malu mengenakan kostum nomor 10. Skill sepakbola saya tak maju-maju. Gocek lawan, memang bisa, sesekali lumayan jago malah. Membobol gawang lawan juga seringkali tak sulit. Apalagi, mengumpan pada rekan di lapangan, saya seperti tak tertahankan. Tapi, tetap saja, saya merasa skill sepakbola saya tak mumpuni. Bukti kasat matanya adalah rekan-rekan saya sendiri di lapangan. Masih banyak yang nyatanya lebih jago bermain bola daripada saya. Sementara saya, seperti terdampar di kelompok pemain bola dengan kemampuan rata-rata saja. Apalagi, saya lemah sekali dalam menyundul bola.
Dari situlah, saya memilih untuk mengenakan nomor 11 saja.
Spontan.
Saya ingin mengeramatkan nomor 10. Itu nomor hanya untuk Maradona saja. Saya tak berhak membalutkannya di badan saya. Makanya, saya sempat kecewa sekaligus ragu ketika nomor 11 itu sudah keburu diambil Olwin saat kami membela kesebelasan Trans TV di Piala Media pada pertengahan tahun 2002, sementara saya kebagian nomor 10, nomornya Maradona. Saya jadi ragu berlari lepas di lapangan, takut membuat kecewa Maradona.
Tapi, berbicara tentang rasa kecewa, saya kembali merasakannya akhir pekan lalu di bangku kursi nyaman dalam ruangan berpendingin, di depan layar lebar yang memperlihatkan sosok Maradona berkali-kali dengan ukuran yang besar dalam tayangan pertandingan sepakbola Piala Dunia antara Argentina melawan Jerman.
Maradona tak bermain kali ini.
Ia adalah pelatih tim Argentina.
Rasa kecewa itu mulai muncul saat Klose mencetak gol kedua Jerman. Riuh semangat yang tadi masih membara, meski Argentina masih tertinggal 0-1, mulai perlahan kehilangan banyak kepingnya.
Saya mulai kehilangan suara untuk berteriak lantang, menyemangati Argentina.
Apalagi saat pertandingan itu berakhir 0-4, untuk kemenangan tim Jerman.
Coke dan pop corn yang sudah habis saya santap itu seakan menjadi hambar dan hanya akan menjadi sampah tak berguna di usus saya. Jarak yang harus saya tempuh untuk pulang ke rumah pun seperti jauh sekali dan harus melewati gurun pasir dan bukit berbatu. Kaos Argentina bernomor punggung 11 yang terpampang setengah kering di rumah pun seperti ingin segera saya pakai dan ajak berbincang kembali.
Saya kecewa bukan main.
Tapi, Maradona memang ajaib, di mata saya.
Meski saya kecewa demikian dalam, tak pernah saya membenci Maradona. Termasuk ketika saya menangis kecil di depan televisi pada pertengahan tahun 1990, gara-gara tendangan penalti Andreas Brehme yang melesak masuk ke gawang Argentina dan membuat Maradona dan Argentina harus puas jadi juara dua di Piala Dunia 1990. Atau ketika Argentina hancur di Piala Dunia 1994, gara-gara Maradona yang nakal tertangkap memakai doping.
Hanya saja, gara-gara Maradona tak jadi lari telanjang di Buenos Aires, sesuai nazarnya jika ia bisa membawa Argentina juara dunia, saya jadi tak bisa tidur nyenyak di ranjang selama beberapa malam.
Sampai tadi malam.
Dan entah malam ini atau malam esok.
dhank Ari at 7:24 AM
Depok, 22 Juni 2010Pernah ada memori Sabtu pagi.
Matahari seringkali masih malu bersinar saat ketokan dan teriakan itu ramai di depan pintu.
Biasanya, Verry yang berteriak paling lantang, diikuti suara nyinyir Usman, dan kegaduhan tangan Febry di daun pintu kamar saya yang ramai oleh stiker gratisan dan sebuah wajan mulus yang sengaja saya pasang sebagai aksesoris.
Seringnya, saya memang dibangunkan, dan bukan bangun lebih awal lantas keliling bergerilya dari satu kamar ke kamar yang lain. Maklum, malam sebelumnya, sama seperti malam-malam yang lain, memang terlalu memesona bagi saya. Malam terlalu berharga untuk dilewatkan tanpa bermain satu dua buah lagu, menulis satu dua bait puisi atau sekedar berbincang ringan dengan para cecunguk Wisma Mitra, nama tempat kost bersejarah itu, yang sungguh bisa mencuatkan rindu kapan saja dan dimana saja.
Tapi, saya tak pernah malas untuk bangun setiap Sabtu pagi.
Saya tahu, di waktu sepagi itu, saya akan bertemu lagi dengan sahabat saya. Bola dan lapangan.
Saya juga akan kembali menjadi pemain sepakbola profesional, setidaknya dalam pemikiran, dengan kemampuan olah bola di atas rata-rata, juga dalam pemikiran, dan disaksikan oleh ribuan penonton fanatik yang hanya terus tampil nyata di ujung angan-angan, di sebuah lapangan kampung yang kadang mengusir kita saat pertandingan baru mulai setengah babak.
Dalam kantuk itu, ada semangat yang luar biasa.
Itulah saatnya saya menjalani impian.
Itulah saatnya saya memiliki hari yang bisa memuaskan saya lahir dan batin.
Itulah saya di tengah dunia tanpa sandiwara.
Sungguh, saya merindukan Sabtu pagi. Sama rindunya dengan pemandangan yang saya lihat setiap kali saya keluar dari kamar di hampir setiap sabtu pagi itu.
Adnan yang malas bangun, selalu terlihat jongkok di pintu kamarnya yang terbuka dengan pandangan yang entah diarahkan ke cabang pohon yang mana. Wiwied yang selalu repot dengan handuknya sambil terus menenteng sikat gigi berodol dan kotak sabun, mewakili masyarakat pesepakbola yang gosok gigi dulu sebelum masuk ke lapangan.
Verry yang sudah siap dengan sepatu dan kostum kebanggaannya. Reza yang kerap memainkan bola dengan kaki kirinya meski bola itu seperti enggan bersahabat dengannya. Daryanto yang masih sarungan setelah sholat subuh, namun terus melontarkan aneka provokasi yang tajam tanpa terlihat bergegas untuk mengganti sarungnya itu dengan celana bola. Jengkol yang paling semangat keliling kamar. Jun yang keluar masuk kamar seperti umbel.
Beng Beng yang santai dan selalu berusaha mengelak. Pintu kamar Randy yang masih tertutup rapat, menunggu kegaduhan yang paling gaduh untuk membuatnya bangun. Da Abdi yang tertawa-tawa kecil, sambil sesekali melontarkan provokasinya dengan tangan kiri yang tak lepas dari gelas besar berisi teh manis panas atau susu putih panas. Barir yang sibuk menyantap roti tawar yang dicelupkan pada susu kental manis yang tak diseduh.
Dan beberapa anak Wisma Mitra yang lain.
Dan beberapa pemain asing dari tempat kost lain atau remaja sekitar.
Apa kalian masih ingat bahwa kita juga pernah menang besar 8-0 bahkan pernah 9-2 saat melawan tetangga kita, Wisma Nusa?
Kemenangan besar Portugal atas Korea Utara malam tadi seperti mengajak saya kembali pada mimpi yang tertinggal. Seperti ingin mencicipi rasa kemenangan itu lagi, meski tak harus di ajang sehebat Piala Dunia. Cukup di Piala Antar Kost saja, atau di sekedar pertandingan persahabatan.
Saya bahkan ingin mencicipi rasa kekalahan itu lagi.
Terutama karena mimpi itu, baik dalam kemenangan atau kekalahan, selalu saja dipenuhi tawa yang tanpa sandiwara, termasuk cedera-cedera ringan sampai pegal-pegal yang tak hilang dalam hitungan jam.
dhank Ari at 7:24 AM
Jakarta 21 Juni 2010Dalam taksi itu, saya berhenti berpikir tentang waktu. Saya tak ambil peduli jika nanti saya datang terlambat di kantor.
Saya lebih memilih untuk menitipkan doa kecil pada Tuhan, untuk seorang lelaki yang kripik bawaannya di atas motor tercecer di jalanan ramai dan hancur berantakan terlindas oleh roda-roda, termasuk roda-roda taksi yang saya tumpangi.
Ada puluhan bungkus kripik terjatuh.
Ada ratusan keping kripik yang tak sempat sampai di lidah.
Ada tangisan tanpa air mata. Dan kemudian ada potongan waktu yang kemudian memberikan kekosongan lagi padamu, hai lelaki pembawa kripik.
Entah apa yang harus kau tebus dengan tragedi kripik pagi tadi, selain waktu.
Mungkin kau harus menunda jajan anakmu.
Mungkin juga kau harus mengurangi lauk makan siangmu.
Atau mungkin kau harus menyimpan geram yang tak jelas hendak kau berikan pada siapa.
Saya tak berani panjang berandai. Saya hanya berani mengingat bahwa saya juga pernah membawa puluhan bungkus “berondong jagung” atau pop corn setiap kali berangkat sekolah saat masih berseragam putih merah. Saya ingat wajah sedih tanpa air mata Ibu jika saya masih banyak membawa berondong jagung itu pulang siang harinya, meski wajah itu dengan ajaib berubah menjadi senyum dan tawa hangat saat kami menyantap bersama berondong jagung itu malam harinya.
Saya tak tahu apa reaksi Ibu jika seandainya saya pulang dengan tangan hampa yang benar-benar kosong; berondong jagungnya habis, namun tak ada uang yang bisa saya beri pada Ibu. Saya benar-benar tak tahu. Mungkin, Ibu hanya akan menuliskan minus pada buku belanjanya yang seringkali saya lihat penuh dengan coretan itu.
Untungnya, saya tak pernah mengalami tragedi itu, namun saya jadi membayangkan reaksi istri atau mungkin bos lelaki itu jika ia datang dengan tangan hampa.
Alasan-alasan bisa jadi hanya bergulir saja tanpa makna. Apalagi, dunia sudah dipenuhi oleh praduga yang kelewat negatif. Kejujuran seperti sudah tak punya lagi kursi dan harus rela teronggok di emperan saja.
Semoga rezekimu encer, ya, meski keripikmu tercecer pagi ini. Amin
dhank Ari at 7:23 AM
Jakarta, 3 Juni 2010Saya baru hendak terlelap ketika suara-suara itu muncul. Terdengar dekat dan keras. Terdengar lebih sebagai bunyi yang mengganggu ketimbang harmoni yang bisa saya nikmati sebagai peneman tidur.
Tikus-tikus kecil itu meneror lagi.
Tikus-tikus itu begadang lagi dan mengerat sesukanya. Atau mungkin, dia sedang mengajak Pluto, anjingnya, jalan-jalan atau membantu Gufi merapihkan rumahnya.
Saya lantas lepaskan sejenak keinginan terlelap. Percuma mencoba nyenyak jika saya harus terus memahami bunyi yang belum bisa saya nikmati itu.
Saya ingat ada lem tikus di lemari dapur.
Saya memang sengaja menyimpannya selama berbulan-bulan ini, terutama untuk saat-saat genting seperti saat ini.
Ah, jalan terakhir itu akhirnya harus saya tempuh juga.
Bukan karena malas, tapi karena memang selalu enggan merusak harmoni, kecuali terpaksa.
Bertahun-tahun kos di Wisma Mitra, saya menciptakan harmoni yang sangat asyik dengan cicak-cicak di dinding, yang tidak selalu diam-diam merayap. Saat kamar teman-teman ramai digandrungi nyamuk dan selalu berbau racun dari semprotan obat nyamuk dan radiasi obat nyamuk listrik, saya lebih sering tenang-tenang saja melewati malam tanpa bersinggungan udara dengan nyamuk. Nyamuk hanya datang sesekali, saat cicak-cicak itu mungkin sedang kelelahan karena terlalu giat menyusuri dinding dari ujung satu ke ujung yang lain. Saya menciptakan hubungan simbiosis mutualisme yang dahsyat dengan cicak saat itu.
Di depan rumah saya sekarang, saya seringkali berpapasan dengan satu atau dua ekor kodok besar. Kadang juga bertemu dengan anak-anak mereka. Saya tak ingin mengganggu ketenangan mereka karena saya tahu, jika mereka juga seringkali menjaga ketenangan saya saat mereka sering menjulurkan lidah panjangnya dan mulai menyiapkan menu makan malamnya.
Saya memilih harmoni.
Selama saya bisa dan itu memungkinkan.
Saya percaya harmoni itu bisa diciptakan dan bisa juga dipertahankan.
Namun, kadangkala, harmoni juga bisa luntur. Seperti saya dan tikus-tikus kecil itu.
Apalagi, tikus semakin ditasbihkan sebagai salah satu hama rumah tangga. Selain mengganggu, tikus juga dianggap bisa menularkan banyak penyakit.
Jadi, begitulah akhirnya.
Saya ambil lem tikus itu. Saya buat gerakan melingkar dari lem di atas karton, seperti petunjuk yang saya baca di bungkusnya, sampai lingkaran itu berdiameter sekitar 15 cm. Di tengah-tengahnya, saya sisipkan tempe goreng sisa makan siang yang tak habis dimakan. Saya kemudian tempatkan karton berlem itu tepat di bawah tangga dari lantai atas, tempat dimana saya sering beradu pandang dengan tikus-tikus itu.
Pagi harinya, seekor tikus terperangkap dengan satu sisi tubuhnya erat melekat di karton berlem itu. Menanti ajal.
Maafkan saya, tikus kecil. Saya lupa bilang kalau kau mungkin tak pulang pagi ini.
dhank Ari at 7:22 AM
Jakarta, 29 Mei 2010Hari Minggu lalu, seperti biasa, saya cuci mobil di Bulletz Car Wash, Radar AURI, Depok.
Seperti biasa pula, saya memesan segelas kopi hitam panas (atau kadang segelas susu putih panas) di warung kopi sebelah Bulletz dan menunggu.
Jika beruntung, saya akan mendapat teman bicara. Tapi seringnya, saya duduk sendiri, sambil sesekali beranjak dan mengintip ke ruang sebelah.
Hari Minggu lalu, adalah salah satu hari beruntung saya. Saat saya masuk ke warung kopi, seorang lelaki, mungkin baru menginjak usia awal 20-an, sudah duduk lebih dulu di sana.
“Istirahat, Mas?”
Saya mencoba praktek deduksi, untuk kesekian kalinya. Satu gerobak tukang loak terparkir mesra di dekat tiang listrik, tak jauh dari warung kopi. Jadi saya pikir, lelaki ini mungkin adalah pemiliknya.
“Iya, Mas.”
“Abis keliling dari mana?”
“Ah, saya sih nyelusurin jalan besar aja, Mas.”
“Oh, gitu? Gak masuk ke perumahan?”
“Jarang, Mas. Paling sering, saya masuk ke bengkel-bengkel atau kantoran aja, Mas.”
“Hm...Kenapa begitu?”
Obrolan terus berlanjut, bahkan ketika pesanan indomie rebusnya datang, sampai akhirnya saya melontarkan tawaran.
“Suka dapet perangko gak, Mas?”
“Perangko?”
“Iya. Perangko. Itu lho yang biasanya ada di amplop surat. Yang suka ada harganya. Bisa 500 perak, bisa seribu atau berapa aja lah.”
“Oh, yang warnanya suka ijo atau merah gitu, ya?”
Saya sempat ingin terdiam dan berpikir sebentar. Apa benar lelaki ini, yang belakangan saya tahu namanya adalah Mardianto, tidak tahu perangko? Apa ia tidak pernah melihat perangko seumur hidupnya?
Tapi diam itu urung saya lakukan. Biarlah saya akan diam berpikir nanti, setelah obrolan kami usai. Dan kami pun terus berbincang, sampai akhirnya ia pamit dan mulai keliling lagi.
Sepanjang perjalanan pulang ke rumah setelah itu, pikiran saya terisi terus oleh perangko dan Mardianto.
Saya pernah punya romantisme tentang perangko.
Ketika teknologi informasi tak semaju sekarang, salah satu cara saya dalam berkomunikasi adalah lewat surat, yang sebagian besar tak lepas dari keberadaan perangko. Saya dulu sering tertawa kecil saat mengambil setumpuk surat dari tukang pos dan menyerahkannya pada Papap atau Mamah. Kasihan Suharto, sang presiden. Wajahnya kerap dipukuli dan dikotori oleh stempel. Kadang sampai membuat mukanya jelek tak keruan karena permukaan perangko itu tertekan cukup keras oleh stempel atau bahkan jadi seperti badut dengan perona muka warna hitam yang terlalu banyak.
Apa sedemikian asingnya perangko bagi sebagian orang saat ini? Mungkin juga pada anak-anak usia muda?
Ingin bertukar kabar, tinggal buka jejaring sosial seperti facebook atau twitter dan ngobrol secara tidak nyata sepuasnya. Chatting, kalau bahasa kerennya.
Atau mungkin lewat layanan pesan singkat di telepon seluler yang isinya bisa sampai saat itu juga pada orang yang dituju. Tanpa jeda seperti surat, apalagi surat dengan perangko biasa, yang bisa sampai berhari-hari di tempat tujuan.
Atau juga lewat perbincangan panjang lebar di telepon seluler yang tarifnya makin murah saja sekarang.
Kalaupun ingin mengirimkan kabar yang lebih resmi atau lebih panjang atau atas alasan apapun juga, masih ada fasilitas surat elektronik atau email.
Apa orang masih berkirim surat secara konvensional?
Di rumah saya sekarang (atau juga di kantor), surat yang datang tak pernah beragam lagi dan mengandung unsur kejutan. Selalu saja surat-surat itu tak lepas dari surat tagihan kartu kredit, indovision, PAM, asuransi dan lain-lain.
Jika dulu, surat yang datang menagih kabar dari saya sambil berbagi cerita dari seberang sana. Kini, surat yang datang menagih uang dari saya sambil berbagi produk konsumerisme yang terus mereka cekoki untuk saya beli.
Jika dulu, tukang pos datang disambut dengan gairah untuk mendapatkan kejutan dan juga perangko yang mungkin tak sama dengan perangko pada surat sebelumnya. Kini, tukang pos datang disambut dengan dingin bahkan sedikit membuat kening mengkerut dan tak ada lagi kejutan perangko melainkan stempel perangko berlangganan yang membosankan.
Lantas di sisi lain, masih adakah sosok-sosok seperti Suharto yang rela narsis meski harus dikotori stempel?
Saya akhirnya lupa pada maksud awal dari tawaran saya pada Mardianto. Saya hanya ingat romantisme masa lalu, saat saya masih getol koleksi perangko, sampai kadang harus menjemur perangko yang sudah dilepaskan dari amplopnya itu berjejer di sekujur kaca nako ruang tamu.
dhank Ari at 7:22 AM
Jakarta, 28 Mei 2010Mendengarkan “Say It To Me Now”, saya ingin segera memeluk gitar dan mulai bernyanyi seperti Glen Hansard, meski saya tahu betul suara saya tak seberapa bagus.
Mendengarkan “Leaving On A Jet Plane”, saya juga ingin segera meniru gaya bernyayi John Denver sambil memainkan harmoni lewat gitar.
Bahkan mendengarkan “Arti Kehidupan” membuat dunia saya kembali berputar. Berputar ke masa dimana saya dan gitar seperti pinang dibelah dua. Berputar ke masa dimana saya rela menyisihkan uang tabungan saya sebesar 45 ribu rupiah untuk membeli gitar saya yang pertama. Gitar bermerek lokal Ariesta, yang saya beli di Banceuy, Bandung, di akhir tahun 1990.
Saya memang sedang rindu bermain gitar.
Saya ingin sekali berputar. Terutama akhir-akhir ini, dimana dunia saya kaku seperti cadas yang tak akrab dengan dinamika.
Saya ingin sekali berputar dengan bermain gitar seperti masa-masa itu dimana gitar selalu bisa membuat dunia saya dinamis, hingga kadang saya sendiri melakukan perjalanan batin yang jauh dari realita.
Pulang sekolah, bukan sepiring nasi yang saya kejar, melainkan “Ariesta” - sang gitar, yang belakangan penuh dengan sticker gratisan.Masih dengan baju putih abu-abu yang penuh peluh, saya mulai memetik melodi Fire House atau Bad English, atau bahkan Ermy Kulit.
Memulai kuliah di Depok, saya tak mengajak Ariesta. Biarlah dia menemani Rumah Ledeng, dan menunggu saya setiap akhir pekan atau akhir bulan saja. Dua bulan pertama saya di Bunaya, saya memang belum terpikir untuk banyak bermain gitar dan bernyanyi. Atau juga, mungkin karena aku masih merasa malu dan takut seandainya ada banyak rekan yang bermain gitar jauh lebih baik dari saya. Maklum, selama di Bandung pun, saya hanya menempatkan ruang senandung itu di sudut pribadi saja, tanpa banyak membuka pintunya untuk keriuhan.
Keluar dari Bunayya, lantas mengontrak rumah selama 2 tahun di ABAH, saya bisa sewaktu-waktu bermain gitar karena Hadi seringkali menaruh gitar birunya itu di ABAH.
Pindah ke Wisma Onansait, saya sedang getol menulis dan sedikit lupa pada melodi gitar kecuali jika ada kesempatan saja.
Kerinduan pada gitar mulai saat saya pindah ke Wisma Mitra. Akhir tahun 1996 itu, saya memang memulai hari-hari saya di Jalan Palakali dengan suasana yang sangat gundah. Menulis lantas tak lagi cukup mewadahi curahan hati saya yang makin buas.
Saya butuh melodi.
Tapi, di sisi lain, saya sedang tak berkenan pulang ke Rumah Ledeng. Pilihan saya saat itu membuat saya harus menciptakan jarak dulu dengan Rumah Ledeng. Termasuk menciptakan jarak dengan Ariesta.
Ingin membeli gitar baru, tapi sungguh itu adalah sebuah mimpi yang konyol di tengah isi dompet yang teramat kosong sementara tak ada lagi gitar bagus seharga 45 ribu rupiah.
Jadilah aku membawa teman baru ke kamar kecil saya di Wisma Mitra. Sebuah Ukulele seharga 25 ribu rupiah.
Empat buah senarnya terasa cukup mengisi melodi, terutama di saat malam, saat saya juga masih belum memiliki kesiapan untuk berkenalan akrab dengan para penghuni lama Wisma Mitra. Banyak melodi lahir di situ, dengan suara malu-malu saya. Namun, saya tak menyangka jika suara malu-malu saya itu belakangan justru menjadi jalan masuk bagi rekan-rekan Wisma Mitra untuk memulai kekerabatan yang sungguh erat hingga saat ini.
“Semalam, kayaknya asyik banget tu nyanyi-nyanyi sendirian di kamar?”, Verry Boekan, rekan yang memang paling supel, sempat memulai pembicaraan di sebuah pagi di depan gerbang Wisma Mitra. Tak jauh dari situ, Dharma juga tersenyum pada saya.
Saya lantas mengingat lagu-lagu yang saya nyanyikan malam sebelumnya itu. Seingat saya, ada beberapa lagu lama milik Panbers dan lagu keroncong “Kr. Kemayoran”. Ah, sedikit tersentak mundur saya pagi itu. Apa mungkin saya dibilang kuno karena tak melantunkan dewa atau lagu-lagu populer saat itu?
Lagi-lagi, gitar membuat dunia saya berputar, terutama karena Verry dan Dharma sama sekali tak memojokkan saya dengan pilihan lantunan saya malam itu. Kita justru malah memulai sebuah adegan pertemanan yang semoga bertahan sampai jauh. Pertemanan yang juga akhirnya membawa Ariesta ke Wisma Mitra, beberapa bulan setelahnya, hingga akhirnya saya titipkan Ariesta pada Verry dan Adnan saat saya memutuskan untuk tak lagi menyewa kamar di Wisma Mitra di awal tahun 2004.
Rindu saya pada gitar yang banyak membuat dunia saya berputar, juga pada melodi-melodi yang keluar
dhank Ari at 7:20 AM
Jakarta, 8 Agustus 2006Selalu terlintas, namun selalu saja berbeda saat dirasakan.
Kunjungan singkat ke Desa Talonang Jaya, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat membasuh banyak sekali keangkuhan.
Bertahun-tahun diliputi nafas-nafas kota, keangkuhan seperti menahun. Seperti candu. Dalam hati saya bersyukur, disempatkan mampir di desa yang nyaris tak terjamah ini.
Namanya Atun. Uswatun Hasanah. Umurnya masih sangat belia, belum genap 8 tahun, namun dia mampu menasehati saya amat dalam meski bukan lewat kata-katanya.
Atun ingin sekali menjadi pintar. Tak heran jika akhirnya dia tak pernah bolos sekolah.
Tak bersepatu, tak mengapa. Tak punya buku, toh masih bisa mengingat tanpa perlu dicatat. Tak punya uang sekolah, masih tetap datang ke gedung sekolah yang kadangkala terbang atapnya jika angin berhembus demikian kencang. Ia tahu, gurunya tak akan tega mengusirnya karena uang sekolah itu tertunggak berbulan-bulan.
Saya terdiam di balik kamera. Mata bermakna ganda saat mengintip lewat lubang kamera atau viewfinder itu.
Saya teringat hari-hari di Jakarta. Terutama hari-hari milik beberapa keponakan dan sepupu saya yang juga bersekolah. Mereka dan Atun sama-sama belajar. Baca dan tulis. Sama-sama pergi ke sekolah.
Saya bahkan teringat diri saya sendiri saat seusia Atun.
Saya ternyata demikian angkuh saat meratapi hari-hari Jakarta saya. Saya kemudian mengganti sosok dalam kamera itu dengan sosok saya.
Saya terhenyak.
Lantas terduduk dan mematikan kamera untuk sesaat.
dhank Ari at 7:10 AM
Jakarta, 4 Mei 2010Saya terbilang sering membuat istilah secara spontan.
Salah satu yang paling spontan dan akhirnya membekas demikian dalam adalah AYTEHS, singkatan dari Apapun Yang Terjadi Elo Hadapin Saja.
Waktu itu hujan, di tengah tahun 1996.
Bukan hujan air yang dilepaskan langit untuk membasuh luka para hati terluka di bumi, melainkan hujan kegelisahan. Wajah-wajah muda yang duduk rapih tepat di hadapan saya, di ruang kelas K.101, Fakultas Teknik UI, adalah bukti nyata jika hujan memang sedang berlangsung seperti badai. Sama dengan hujan yang sedang terjadi di pekarangan saya yang paling pribadi.
Tak semata deras hujan itu, tak pula gerimis.
Dan saya tak ingin meneruskan hujan itu. Saya sungguh tak ingin menutup pintu terlalu cepat bagi jiwa-jiwa baru yang (saya yakin) masih memiliki semangat yang baru saja matang. Tak ingin saya membiarkan semangat itu terlanjur dingin, apalagi basi. Saya harus menghentikan hujan itu. Apapun caranya.
Ada Iwan di samping saya. Akbar berdiri gelisah di tepi pintu bersama Elfisar. Beberapa teman lain merapat di belakang kelas, enggan membuat suara.
Beberapa menit sebelumnya, hujan memang mencapai puncaknya. Hujan yang akhirnya membuat kami banyak kehabisan kata, padahal pagi harinya kami masih kebanjiran kata-kata.
Saya tak menyangka jika kami akan mendapatkan serangan mendadak siang itu.
Wajah-wajah muda itu sedang berbaris rapih. Suara lantang Iwan dan Akbar saling mengisi di tengah kosongnya sejengkal tanah lapang berumput di depan Gedung GK. Sambil panas matahari sesekali menggigit.
Saya memperhatikan dari belakang, bersama Bagonk dan Heri.
Hujan mulai rintik saat sudut mata kiri saya merasakan ada kehadiran yang terburu-buru sekelompok orang dari arah jam 8.
Saya kontan menoleh.
Saya lihat sekelompok orang itu adalah para pejabat Jurusan Sipil FTUI, dipimpin oleh Ketua Jurusan, Pak Budi Susilo.
Gawat, pikir saya. Apa yang harus saya katakan padanya?
Sebelum sempat memberi kesempatan pada kata-kata yang sudah perlahan dirancang di dalam pikiran itu untuk terucap, tangan kanan Pak Budi sudah menjambak leher kaos kesayangan saya dan merapatkan jambakannya itu pada dada saya sambil mengangkatnya mendesak dagu. Saya nyaris tercekik!
“Sudah saya bilang kemarin untuk hentikan!! Tidak ada MABIM!! Kamu sudah janji pada saya kemarin!! Ingat? Ini apa? Kenapa masih ada yang begini? Bubarkan mereka!! Suruh masuk kelas!! Dan kamu, jangan lagi melawan saya! Ngerti?”
Hujan sudah turun. Deras pula tak tertahankan.
Iwan dan Akbar lantas membubarkan barisan dan wajah-wajah muda itu pun kembali ke ruang kuliah. Saya mengikuti sambil memikul hujan itu di pundak. Jefry, Yulius dan Heri terlihat memaki di ujung penglihatan saya. Bagonk meringis kesal, yang saya rasa bisa mewakili perasaan teman-teman yang lain.
“Elo musti ngomong, Ri, sekarang!” Iwan buka suara setelah wajah-wajah muda itu sepenuhnya masuk ruang kuliah.
“Ya. Ayo!”. Hujan dirasa semakin deras, terutama di pekarangan saya. Saya sadar jika saya harus terlebih dahulu memayungi diri dari hujan deras itu sebelum saya siap membuatkan payung di pekarangan wajah-wajah muda itu.
Saya kemudian masuk, ditemani teman-teman yang lain.
“Junior!!”, teriak Iwan.
“Siap!!”
“Junior!!”
“Siap!!”
Saya mulai buka suara.
“Masih semangat, Junior?”
Sebagian menjawab cepat dan lantang, tapi saya tak mendengar bulat sebagai sebuah suara yang satu di ruang kuliah itu.
Saya balik badan dan mulai menuliskan A Y T E H S dengan kapur kecil di papan tulis hitam di depan kelas.
Spontan!
Spontan sekali meski saya masih basah oleh hujan yang belum juga bisa saya payungi sepenuhnya.
Saya menuliskannya sambil mengira-ngira isi ucapan saya nanti pada wajah-wajah muda itu. Saya mulai dengan “A” untuk “Apapun” dan kemudian berhenti di kata keenam. Saya rupanya sudah merasa siap mencoba meredakan hujan itu dan lantas balik badan kembali untuk menatap hujan itu lebih lekat lagi, menyisakan tulisan AYTEHS di papan tulis.
Saya mulai menunjuk huruf itu satu persatu sambil berujar wajar,
“Apapun Yang Terjadi Elo Hadapi Saja. Kenapa? Karena......”
Enam kata pembuka yang lantas berlanjut dengan puluhan, ratusan atau mungkin ribuan kata berikutnya yang saling ditimpali oleh saya, Akbar, Iwan, Alfi dan rekan-rekan yang lain. Enam kata pembuka yang kemudian memberi saya kekuatan sangat besar untuk melawan hujan kegelisahan saya yang teramat besar, terutama jika mengingat bahwa saya memang harus tenang untuk membekali wajah-wajah muda itu kekuatan untuk melawan hujan kegelisahan mereka.
Saya tidak tahu apakah 6 kata itu berhasil merajutkan payung untuk melindungi mereka dari hujan di pekarangan mereka.
Saya juga tidak tahu apakah saya bisa menanggung resiko jika 6 kata itu justru membuat mereka terperosok lebih dalam dari sekedar hujan kegelisahan.
Tapi dua hal yang pasti.
Enam kata itu adalah katalis kekuatan saya kembali.
Dan enam kata itu adalah pengikat emosi saya yang paling dalam dengan wajah-wajah muda itu hingga kini.
Termasuk ketika Buras, alias Budi Wirastomo, menuliskan kata-kata magis itu lagi sebagai komentar atas status saya yang sedang gelisah di facebook pada tanggal 15 April 2010.
dhank Ari at 7:08 AM
Jakarta, 3 Mei 2010Lama saya tak menggeluti deadline.
Belakangan ini, saya lebih banyak menggeluti frontline. Menjadi garda terdepan untuk membuka banyak jalur kemungkinan untuk berkarya di bidang audio visual, termasuk menggagas banyak kerjasama dengan beberapa pihak yang memiliki visi yang sama dengan kami.
Deadline hanya muncul sesekali di akhir pekerjaan, itu pun tak terlalu banyak karena memang pekerjaan itu pun masih datang sesekali saja. Bukan sebuah pekerjaan yang berkelanjutan. Atau setidaknya belum.
Kini, ada berjuta deadline yang akan segera saya hadapib di depan mata.
Sebuah konsekuensi.
Sebuah tikungan awal untuk mewujudkan mimpi paling berani yang pernah saya buat di pertengahan tahun 2007.
Saya jadi ingat 11 semester saya di Akademi Trans TV.
Ada banyak deadline di situ. Lari berkali-kali, naik turun lantai 3 dan lantai 2, lewat tangga darurat adalah biasa. Muka senyum terpaksa, sementara jantung berdetak lebih cepat dari Ferrari yang dipacu Schumacer di lintasan balap, adalah makanan rohani saya hampir setiap minggu, setiap hari atau bahkan setiap menitnya. Marah bukan lagi tabu. Bentakan juga tak lagi tersembunyi. Kami seperti prajurit-prajurit yang kehausan di medan perang, namun harus menunggu air embun dari dedaunan itu memenuhi gelas kami yang kosong.
Tahun 2006, saya mencoba berhenti geluti deadline. Saya memilih untuk berkarya dengan alokasi waktu yang lebih bisa membuat saya berpikir jernih.
Namun, deadline rupanya selalu mengikuti, meski kini hanya datang sesekali.
Aksi kejar-kejaran deadline seru terakhir adalah ketika Suharto meninggal.
Saat itu, saya memang sedang mengerjakan dokumenter 24 menit tentang Suharto untuk Astro Awani, salah satu kanal berita di televisi berbayar Astro TV. Setelah berbulan-bulan riset, menulis naskah dan mencari materi audio visual dari Arsip Nasional, TVRI dan beberapa Production House, saya dan Alfian Hamzah, serta dibantu PA handal Vivi Bas Edan, kami mulai merajut cerita itu dalam proses penyuntingan. Di BES studio, saat itu.
Tiba-tiba, Suharto meninggal di RSPP.
Deadline itu lantas muncul dari pojokan gelapnya, seakan ia sudah menunggu di sana untuk keluar sekonyong-konyong seperti itu. “Dokumenter Suharto harus tayang nanti malam. Harus! Sudah sampai mana, sekarang proses editnya?”
Sesuai kesepakatan, memang. Dokumenter ini memang dirancang dari awal untuk tayang pada saat Suharto meninggal. Kapanpun itu.
Alhasil, hari Minggu itu tak seperti hari keluarga yang penuh canda tawa di Taman Ria. Saya mandi seadanya dan kemudian meminta supir taksi itu berpacu secepat-cepatnya, mencoba mengalahkan waktu. Mencoba mengakali waktu. Mencoba menahan atau memundurkan waktu.
Kurang dari 12 jam, saya harus mengerjakan penyuntingan akhir itu, sementara proses penyuntingan itu baru seumur jagung. Baru dimulai beberapa hari sebelumnya, dan masih kurang 3 materi visual.
Alfian mondar mandir seperti sepur malas beroperasi di ujung stasiun. Ia juga kadang teriak dan memegangi dinding BES yang dingin. Sigaret, satu per satu mengepul tak tertahankan.
“Ah, gila ini!! Gila!!”
Saya tahu persis perasaan Alfian. Ia belum puas dengan materi yang kita dapat. Masih kurang 3 materi visual. Alfian ingin dokumenter ini sempurna dan ia tahu jika keterbatasan waktu ini bisa saja membuat banyak celah kekurangan di sana-sini.
Vivi tak henti berdoa sambil sesekali memasang wajah cemas yang besar. Ia sering terlihat menundukkan kepalanya atau sekedar menutup matanya.
Saya? Saya mencoba untuk tenang. Kembali dengan muka senyum terpaksa yang sudah lama saya latih, padahal lagi-lagi jantung saya berpacu di lintasan balap, dengan sesekali melampaui Valentino Rossi.
“Kok bisa, bro, Elo tenang?” Alfian meminta pertolongan atas detak jantungnya yang tak beraturan.
“Biasa. Udah jadi makanan sehari-hari dulu.”
Om Wendy, sang editor, untungnya tenang. Satu per satu, tahap-tahap penyuntingan ia lakukan. Saya tak berani terlalu banyak cerewet seperti biasanya. Mengejar waktu lebih utama, daripada mengejar berbagai kemungkinan maksimalisasi sisi kreatif.
Akhirnya, dua segmen pertama berhasil kami kirim dua jam sebelum tayang. Dan satu segmen terakhir, saya bawa sendiri ke Citra Graha ditemani Pak Joko, pengemudi kantor. Saya hanya meminta satu.
“Gak usah ngerem, Pak, kalau perlu!”
Sampai di parkiran Citra Graha, saya langsung lari lewat tangga darurat sampai lantai 5. Tak sampai 5 menit kemudian, materi itu tayang. Ucapan terima kasih kemudian muncul. Beberapa kali.
Setelah itu, sepi.
Sunyi lagi.
Lintasan balap sudah tutup, dan menyisakan kekosongan yang bahkan angin sekalipun tak bertiup.
dhank Ari at 7:04 AM
Jakarta,1 Mei 2010Ada beberapa nama tempat yang melekat di benak saya sekian lama, menunggu untuk ditulisi tinta dalam catatan pribadi saya di dalam hati. Saya tidak tahu persis apa alasannya. Tempat itu melekat saja seperti lem yang bisa melekatkan dirinya sendiri tanpa disuruh, seperti memiliki magnet yang saya sendiri luput mengetahuinya dari awal. Saya hanya diberi ruang gelap untuk mencari jawabannya.
Beberapa sudah saya kunjungi, akhirnya. Ajaibnya, ternyata memang ada alasan misterius atas lekatnya nama tempat itu di benak saya sekian lama.
Pertama, Semarang.
Sejak saya masih berseragam putih biru, Semarang terasa misterius. Seperti ada bisikan bahwa saya harus terus mengingat nama itu. Nyatanya, saya terbang menggunakan pesawat terbang untuk pertama kalinya seumur hidup saya menuju Semarang setelah saya menerima tiket itu dari kantor. Tiket penerbangan Garuda dari Jakarta ke Semarang. Lupakan segala kebodohan lelaki muda bersemangat yang biasanya hanya akrab dengan metromini dan kereta rel listrik jabotabek saat harus melewati seluruh prosedur di bandara seorang diri sambil menenteng Camera DVC Pro Panasonic nomor 11 itu.
Lupakan pula segala ketakutan terbang yang nyatanya hanya terjadi di 5 menit pertama saja. Lupakan juga kekhawatiran akan ketidaktahuan tentang prosedur lain yang harus dilalui sesampainya di Semarang. Saya lebih asyik bermain dalam pikiran saya sendiri bahwa nyatanya Semarang memang punya arti tersendiri untuk saya.
Kedua, Lombok.
Pertama kali memahami keinginan mengetahui lebih banyak tentang Lombok adalah ketika saya menghabiskan dua tahun di ABAH, rumah kontrakan masa saya kuliah yang kami namai sesuai dengan nama para panghuninya: Ari, Bowo, Andre dan Haries. Maaf, Ndre, A yang di depan, kali ini saya veto....he...he..he..
Waktu itu, saya mulai sering mendengar tentang Lombok. Dari anak-anak 93 yang gila, dari tayangan TV, dan dari buku-buku.
Nyatanya, saya mendapatkan jodoh di sana. Tugas liputan selama 10 hari itu telah menorehkan pesona seorang perempuan luar biasa di mata saya. Dewi Laila, namanya. Sama sekali di luar dugaan jika perempuan yang selama ini lebih sering menjadi teman debat dan beberapa kali saya marahi justru menjadi perempuan paling istimewa dalam hidup saya.
Kini, masih ada lagi beberapa nama tempat yang demikian melekat dalam benak saya.
Dan saya masih berada di ruang gelap yang sama seperti ruang gelap-ruang gelap Semarang dan Lombok.
dhank Ari at 7:03 AM
Bandung, 30 April 2010Selesai tugas 9 hari di Garut, saya menyempatkan diri mampir di rumah Ledeng, rumah masa kecil yang akan terus menjadi istana.
Saya punya waktu beberapa jam, sebelum harus kembali ke Jakarta dan menekuni mimpi.
Seperti biasa, saya tak pernah mengabari dulu jika saya mau datang. Mamah seringnya repot sendiri jika tahu saya mau ke Rumah Ledeng. Termasuk menyiapkan makan dan segala tetek bengeknya. Saya tak perlu disambut seperti itu, Mah, biarkan saja anak nakal ini datang dengan biasa, tanpa perlu seremoni penyambutan. Apalagi, saya sudah bukan pelarian lagi, bukan lagi lone rider.
Mamah tersenyum lebar saat saya datang. Papap masih menggali memori dulu sebelum memutuskan jika anak yang satu ini adalah benar anaknya. Sindroma Parkinson perlahan telah melemahkan daya ingatnya. Sesekali Papap bahkan lupa sama sekali tentang segalanya.
Saya ajak kemudian Papap berbincang. Tentang kondisi kesehatan, tentang Dewi, tentang Mang Eded yang sempat berbincang dengan saya lewat message di facebook dan tentang pekerjaan saya. Saya bilang, saya baru pulang dari sebuah desa di kaki gunung, bikin dokumenter tentang kesadaran warga untuk membuat biogas dari kotoran sapi.
Saat saya demikian antusias bercerita itulah, saya ingat jika saya punya beberapa jepretan selama di sana, yang sudah saya simpan di dalam laptop.
Saya lantas ambil laptop dan kemudian menunjukkan foto-foto itu.
Tapi, Papap justru bingung. Dengan muka berkerut, ia terus mencoba menggapai layar laptop itu dengan tangannya. Sesekali, kuku jari telunjuknya disentuhkan berkali-kali pada layar laptop.
Awalnya, saya tak sadar dan terus mengoceh tentang ini itu, termasuk memperlihatkan foto narsis saya dengan kamera Z7 andalan. Saya pikir Papap sedang antusias menunjuk pada foto saya dan pekerjaan yang terekam di jepretan-jepretan itu.
Belakangan, saya mencoba memahami, karena kerutan di muka Papap membuat saya harus berhenti mengoceh dulu dan berpikir.
Apa mungkin karena laptop bukanlah barang yang ngetop di memori Papap?
Papap memang tak pernah punya komputer. Setahu saya, Papap hanya mengakrabi mesin tik yang lantas ia wariskan pada anak yang sialnya justru menghilangkan mesin tik itu saat kuliah di Depok. Saya juga tak pernah tanya apa Papap pernah menggunakan komputer di kantornya, di kampus IKIP Bandung. Tahun 1996, Papap benar-benar berhenti mengajar karena jatuh di kamar mandi itu telah menurunkan drastis kemampuan fisiknya yang memang sudah digerogoti Parkinson. Ia pun banyak menghabiskan waktunya di rumah setelah itu.
Pertama kali komputer menjadi anggota Rumah Ledeng mungkin baru sekitar tahun 2000. Neng Lia yang beli. Ia bilang, untuk hiburan dan menulis. Papap sudah sangat sakit waktu itu. Setelah kejatuhan keduanya dari tangga di tahun 1999, Papap nyaris total terbaring terus di ranjang, sulit berdiri dan sering kelelahan jika terduduk di kursi. Jadi saya tak ingat pernah menemukan momen Papap dan komputer.
Apalagi kemudian laptop.
Laptop benar-benar tak ngetop di memori Papap.
Laptop mungkin seperti barang luar angkasa yang baru saja dijatuhkan alien ke bumi
dhank Ari at 7:02 AM
Jakarta, 29 April 2010Menonton banyak film telah membuat saya tergugah bertubi-tubi.
Salah satunya adalah pada pemikiran saya tentang rumah Ledeng, rumah masa kecil saya di utara Bandung, Jawa Barat.
Saya pernah merasa repot karena letak rumah Ledeng yang terbenam di dalam gang padat yang sama sekali tak menyisakan lahan untuk sepetak taman atau bahkan jalanan umum yang lebih lebar. Meski tak terlalu banyak penghuni hingga harus berebut nafas, tetap saja saya merasa kurang udara. Ini terutama saya rasakan saat masih tinggal di sana, menyelesaikan sekolah menengah saya.
Saya kerap terganggu karena banyak alasan. Salah satunya adalah karena akses menuju rumah saya.
Tak mudah saat seseorang ingin bertamu ke rumah. Jika mereka membawa motor sekalipun, mereka harus mencari tempat parkir yang cukup luas di jalanan yang agak besar, yang letaknya sekitar 50 meter dari pintu rumah Ledeng. Apalagi jika mereka membawa mobil. Mereka harus menitipkan mobil mereka di lokasi yang agak kosong dengan jalanan lebih besar, lantas berjalan kaki sambil menanjak sekitar 100 meter sebelum sampai di rumah Ledeng. Paling enak, memang bagi mereka yang jalan kaki. Kesulitannya hanya pada keharusan menarik nafas lebih panjang karena jalanan yang menanjak atau karena sempitnya gang yang harus mereka lewati sementara anak-anak kecil banyak berlari-lari di sana.
Itulah makanya, saya jarang mengundang teman-teman saya datang. Saya takut malah jadi merepotkan. Lebih seringnya, saya yang menghampiri mereka atau menghabiskan waktu di luar rumah.
Tapi beberapa film mengubah pola pikir saya, terutama film-film yang mengambil setting lokasi di Italia. Salah duanya adalah The Talented Mr. Ripley dan Life is Beautiful. Dalam film itu, banyak penggambaran lokasi tempat tinggal para tokohnya yang juga terletak di jalan-jalan kecil, menyerupai gang-gang padat seperti di rumah Ledeng. Saya merasa fantastis dengan penggambaran itu. Tinggal di rumah yang terletak di dalam labirin gang dan jalanan kecil, yang kadang padat oleh manusia, nyatanya tak terlalu buruk. Mereka saja tak ambil pusing jika sulit memarkir mobil di rumah mereka, atau jika hanya bisa memiliki mobil fiat dan bukannya Mercedes Benz atau station wagon yang besar, atau bahkan jika mereka harus puas memaksimalkan penggunaan Vespa atau angkutan umum dan berjalan kaki.
Lantas, kenapa saya harus repot?
Saya memang pernah punya mimpi agar Papap punya mobil sendiri, jadi mungkin, saya atau kami tak harus melulu mengandalkan bis Damri dan angkutan umum yang seringkali menyita banyak waktu kita untuk berhenti berlama-lama di banyak titik untuk mencari penumpang. Mungkin itu yang membuat saya merasa terganggu. Dimana kami akan memarkir mobil kami?
Rupanya, saya sudah terlalu egois dengan mencoba menempatkan pemikiran saya pada pemikiran Papap. Papap adalah orang yang sangat sederhana dan praktis. Tahun 1975, rumah Ledeng ia beli, sesuai dengan kemampuannya saat itu. Ia tahu bahwa ada banyak konsekuensi saat memilih untuk membeli rumah Ledeng, termasuk tipisnya kemungkinan memiliki parkir mobil plus mobilnya itu sendiri. Atau mungkin juga Papap berpikir bahwa ia tak akan bisa secepat itu membeli mobil. Butuh bertahun-tahun menabung sebelum akhirnya bisa membeli mobil.
Tahun 1982, Papap membeli rumah lagi di kawasan Margahayu, dengan skema cicilan 15 tahun dari BTN. Papap rupanya sudah punya proyeksi untuk keluar dari rumah Ledeng dan beberapa keterbatasannya.
Sayang, harapan Papap tak semulus kenyataan. Mobil tetap tak terbeli dan rumah itu pun terpaksa di jual di pertengahan tahun 1999, karena Papap yang sakit membutuhkan banyak biaya pengobatan, sementara saya masih kerja serabutan karena krisis moneter tak menyisakan lapangan kerja bagi lulusan baru yang masih miskin pengalaman.
Tapi kemudian saya bersyukur. Rumah Ledeng kini justru menjadi rumah yang masih terbilang nyaman, saat bumi makin memanas, termasuk di Bandung yang punya catatan sejarah sebagai salah satu kota yang lumayan adem di Indonesia.
Saya masih bisa merasakan suhu 16 derajat celcius di pagi hari sambil menyeruput kopi hitam dan pisang goreng hangat.
Saya juga tak banyak harus mengisap debu hasil polusi jalanan, karena tak banyak kendaraan bermotor lewat rumah Ledeng. Motor hanya lewat sesekali, sementara mobil tak akan pernah mampu lewat di jalanan selebar 1 meter saja itu.
Iseng, saya juga sesekali membayangkan jika saya berada di San Remo, Italia.
dhank Ari at 7:01 AM
Garut, 29 April 2010Ada sensasi tersendiri saat saya makan pisang. Meski mungkin hanya kadang-kadang saja, bukannya setiap saat.
Pisang memiliki tiga ruas daging yang melekat satu sama lain. Waktu saya masih berseragam putih merah (atau putih kecoklatan dan merah di akhir tahun ajaran karena seragam itu mulai usang akibat kebiasaan bermain yang tak mengenal kotor dan menunggu pengganti), saya akrab dengan tiga ruas itu.
Setiap kali disodori pisang oleh Ibu, saya seringkali memisahkan terlebih dahulu ketiga ruas pisang itu dan memakannya satu per satu dalam gigitan-gigitan kecil. Mungkin saya bosan dengan cara lama atau mungkin juga karena saya bosan dengan buah pencuci mulut yang itu-itu saja, karena di tempat saya, pisang memang buah yang bisa didapat kapan saja kita mau. Jadilah saya memulai kebiasaan yang ternyata mengasyikan itu. Ada sensasi tersembunyi, rupanya, dari buah pisang yang selama itu hampir selalu ada terhidang di meja makan.
Saya lupa waktu persisnya, tapi perlahan saya mulai meninggalkan kebiasaan itu. Mungkin itu diawali pada saat saya kuliah, karena uang makan yang pas-pasan di tanah rantau tak memungkinkan saya untuk membeli pencuci mulut. Tidak satu buah pisang, sekalipun. Apalagi es krim atau kue coklat.
Pada saat saya memiliki ruang lebih untuk membeli menu pencuci mulut, saya sepertinya sudah mulai lupa dengan kebiasaan yang mengasyikan itu. Saya lebih sering menghabiskan pisang itu cepat-cepat, atau sekedar lewat saja sebagai intermezzo dari derasnya serbuan rempah-rempah dan kolesterol.
Hari ini, di Desa Pangeureunan, Garut, saya seperti mengalami dejavu. Diawali oleh rasa sungkan saya karena terus menerus menyantap makanan di depan mata saya, karena mata yang lapar melihat aneka makanan yang menggiurkan itu, saya memilih untuk mengupas kulit pisang itu hingga hampir tandas dan memisahkan ketiga ruasnya terlebih dahulu sebelum kemudian memakannya satu per satu. Saya tahu jika saya gigit pisang itu dengan mulut saya yang besar, pisang itu tidak akan tahan lebih dari 3 gigitan. Saya berpikir, jika saya melakukan cara kedua, maka akan dibutuhkan waktu kurang lebih tiga kali lipatnya.
Dan itu berhasil.
Lebih berhasil lagi karena prosesi itu rupanya mengembalikan saya ke memori belasan tahun yang silam.
Saya merasakan sensasi yang sama.
Saya seperti baru mencicipi pisang untuk pertama kalinya seumur hidup saya.
dhank Ari at 6:59 AM
Garut, 26 April 2010Tak harus bingkai foto atau lukisan yang tergantung di dinding rumah, rupanya. Atau dinding kantor. Atau dinding apapun.
Di dinding rumah bilik yang disewa Yapeka sebagai kantor sekretariat di Desa Pangeureunan, Garut, yang tergantung justru beberapa kotak kertas, bekas beberapa produk makanan. Ada 4 kotak kertas bekas tergantung di sana, tersebar di dua dinding rumah. Kotak bekas penganan kecil wafer Selamat tergantung rapih di dekat pintu kayu yang mengarah ke halaman belakang rumah dengan tinggi sejajar dengan bagian atas pintu. Kotak bekas kopi sachet Cappucino tergantung sekitar 10 sentimeter di atas pintu kamar. Sementara kotak bekas tinta printer merek Canon dan kotak bekas Teh Poci terletak berdekatan di dekat pintu kamar kedua yang bersebelahan dengan kamar pertama.
Semua kotak bekas sudah dalam kondisi tergunting rapih di sebagian besar salah satu sisinya hingga kotak itu lebih menyerupai kantong, tempat menyimpan sesuatu.
Saya mulai bertanya, terutama karena kotak-kotak itu terlihat kosong. Jika itu memang merupakan kantong, benda apakah yang mungkin disimpan di sana?
Sebelum kebingungan menjabat tangan saya terlalu lama, Adit langsung tancap gas dengan penjelasan yang mungkin sudah dia tunggu sepanjang 5 jam perjalanan dari Jakarta.
“Di sini, kalau mau dapet sinyal, kalau simpati di sana (menunjuk pada kotak bekas Cappucino), kartu As di sana (menunjuk pada kotak bekas wafer Selamat), kalau XL di situ (menunjuk kotak bekas tinta printer canon yang sudah ditempeli bekas kartu perdana XL), terus sebelahnya Mentari (menunjuk pada kotak bekas Teh Poci. Kalau IM3 bebas, soalnya di sini paling bagus ya IM3.”
Oh, begitu?
Jadi itulah alasannya kenapa mereka memilih untuk menaruh kotak-kotak bekas itu. Dan akhirnya, saya pun mengikuti kebiasaan mereka yang menerima atau melakukan panggilan telepon sambil menempelken ponsel mereka pada dinding itu, meski mulai pada hari kedua saya memilih untuk berani beranjak dari dinding dan melenggang kesana kemari dengan sinyal yang putus nyambung.
Saya lantas ingat kunjungan saya ke Pulau Tomia, Wakatobi di akhir tahun 2009 lalu. Saat saya berkeliling pulau senja itu, ada satu pohon di tengah padang rumput yang nyaris tandus dan penuh belukar itu, yang ramai oleh motor terparkir tanpa pengendara.
“Itu kenapa motor-motor parkir di situ? Gak ada orangnya lagi?”
“Itu Bang. Cari sinyal. Kalau jalan agak ke selatan dari pohon itu, sinyal telkomselnya bagus, Bang.”
dhank Ari at 6:58 AM
Wijaya, Jakarta Selatan, 13 April 2010Siang itu, seperti biasa saya memasang mata jauh ke depan di balik kemudi. Tepatnya, di jalan Wijaya, Jakarta Selatan.
Lampu merah persimpangan membuat kaki saya perlahan menginjak rem dan mobil pun berhenti. Di depan saya, sebuah truk sampah yang sudah penuh lebih dahulu berhenti. Dua orang lelaki duduk kelelahan di atas tumpukan sampah yang menggunung, hasil pengumpulan dari bagian kecil Jakarta.
Tak lama, saya lihat mereka berbincang. Masih dengan rona lelah yang ingin segera mereka usir dengan seteguk air putih dingin dan sebungkus nasi rames sederhana.
Lelaki yang duduk di ujung kiri truk lantas mengambil sesuatu dari tumpukan sampah di sebelah kirinya, yang tak terlihat dari sudut pandang saya, dan menyerahkannya pada lelaki kedua yang duduk di ujung kanan truk.
Ternyata, benda itu adalah sebuah sepatu. Dari kejauhan, saya melihatnya seperti sepatu converse atau sepatu warrior yang pernah saya kenakan dulu sebagai sepatu wajib ketika sekolah.
Setengah ragu, lelaki kedua itu akhirnya mengambil sepatu yang sudah diacungkan di depan mukanya. Ia mengamati sepatu itu sambil sesekali berbicara pada lelaki pertama. Saya tak kuasa mengira-ngira isi ucapannya, hanya mengamati saja sambil menunggu lampu merah yang biasanya memang bertahan lama.
Lelaki kedua terus berbicara sambil membolak-balik sepatu itu. Perlahan, ia kemudian membuka sandal jepitnya dan mencoba untuk memasangkan sepatu itu di kakinya.
Terlihat wajah kegembiraan di wajahnya.
Sepatu itu rupanya muat di kakinya. Lelaki itu tertawa girang. Mimiknya menyerupai akting Brendan Fraser saat menemukan harta karun peninggalan Mesir Kuno di film Mummy.
Tapi, lelaki kedua tak berhenti di situ. Dengan penuh antusias, ia lantas mencari sepatu pasangannya.
Mungkin, akan lebih baik kalau ada pasangannya. Ia bisa memakainya untuk menemui sang kekasih dan mengajaknya jalan-jalan. Atau pergi mengunjungi orang tua di kampung. Atau untuk sekedar cuci mata di pusat pertokoan pinggiran.
Setelah mengaduk beberapa lama, sepatu pasangannya itu pun ia temukan. Ia bertambah girang dan bergegas memasangkannya pada kakinya yang otomatis terbuka dari sandal jepitnya.
Cocok!
Dan belanja siang hari itu pun usai sudah. Lelaki kedua kini punya sepatu baru, tanpa perlu malu menunggu diskon di sebuah mal mewah berpendingin yang seringkali dipenuhi orang-orang yang lebih berduit dan ingin belanja namun tetap mengejar aneka diskon produk.
Saya, mendadak lupa pada mewahnya departemen store atau mal yang biasa saya kunjungi untuk belanja, hampir apa saja, mulai dari korek kuping sampai komputer. Saya mendadak lupa bagaimana rasanya bergembira selesai belanja sesuatu yang saya suka betul. Saya mendadak ingin berterima kasih pada orang yang membuang sepatunya itu, karena saya sendiri mungkin tak sebaik dia.
Buktinya, saya masih menyimpan beberapa sepatu usang yang sudah lama tak saya pakai.
dhank Ari at 6:57 AM
Jakarta, 13 April 2010Entah kenapa, saya suka sekali olahraga sepakbola.
Tapi, percaya atau tidak, saya baru sekali nonton pertandingan sepakbola berkarcis dari sebuah kompetisi di stadion secara langsung. Pertandingan Pra Piala Asia, Indonesia melawan Australia di Stadion Bung Karno, Senayan. Itupun baru di pertengahan tahun 2008, hampir 30 tahun setelah saya mengenal rasa suka saya terhadap sepakbola.
Saya masih ingat, pertengahan tahun 1982, saya menyaksikan sepakbola untuk pertama kalinya. Waktu itu, dunia seperti disihir oleh gelaran Piala Dunia Sepakbola di Spanyol. Bapak, yang saya tahu tak begitu gemar dengan olahraga massal ini, ketiban pulung oleh kewajiban menghibur anak-anaknya dengan tayangan televisi satu-satunya di negeri ini saat itu yang kerap menyajikan pertandingan-pertandingan dari Piala Dunia. Saya jadi ikut tersihir. Olahraga ini rupanya demikian memesona. Mata saya nyaris tak bisa lepas dari layar televisi hitam putih itu.
Lantas, saya, dengan kaki-kaki kecil seorang anak berusia belum genap 7 tahun, pun mulai menendang bola meski masih menendang tanpa aturan dan sekenanya saja. Bolanya pun kadang masih harus saya ganti dengan selembar kertas yang saya remas hingga bulat menyerupai bola.
Masuk SD, saya bertemu banyak teman yang rupanya juga suka sepakbola. Jadilah kami bermain setiap kali ada waktu kosong. Waktu-waktu kosong sambil menanti bel masuk kelas, jam istirahat pertama, jam istirahat kedua dan waktu bebas setelah pulang sekolah. Saya bahkan kerap menantikan saat-saat dimana guru tak masuk kelas atas alasan apapun sehingga kami bisa kembali menjajah lapangan beton di depan sekolah kami. Malam hari, saya selalu menantikan berita tentang sepakbola di dunia dalam berita TVRI. Bapak dan Ibu lama-lama tahu jika saya tak boleh diganggu di 3 sampai 5 menit berharga itu. Sampai akhirnya saya menemukan Maradona di tahun 1986, pahlawan sepakbola saya sampai saat ini.
Namun, sampai saya lulus SD, saya tak pernah menyaksikan sepakbola secara langsung di stadion. Termasuk menyaksikan klub bola kesayangan saya, Persib Bandung. Bapak tak pernah mengajak saya nonton sepakbola. Bapak lebih banyak mengajak saya belajar menggambar dan melukis bersama anak-anak didikannya di IFFH. Meski saya akhirnya sempat ikut pameran dan beberapa kali ikut lomba melukis, saya tahu bahwa jiwa saya masih melekat di guliran si kulit bundar. Di gol-gol indah yang selalu aku bayangkan disoraki oleh ribuan penonton.
Mungkin ada sedikit kesedihan dibalik kenyataan itu, tapi saya bersikeras untuk tidak merengek pada Bapak, juga Ibu. Tak adil, pikir saya. Biarlah saya menunggu saja ajakan itu.
Masuk SMP, saya sebenarnya punya keinginan untuk ikut sekolah sepakbola di kota saya, Bandung. Tapi, lagi-lagi saya menunggu. Saya berharap, Bapak akan melihat minat saya yang besar pada sepakbola dan mungkin, akan menyekolahkan saya di sekolah sepakbola. Setiap siang, saya pasti bermain bola bersama teman-teman saya di sekolah, sementara sore harinya, giliran teman-teman sekampung yang menjadi partner saya menggiring bola dan mencetak banyak gol-gol bersejarah. Dalam hidup saya.
Saya bermain bola, terus dan terus. Saya ingin tunjukkan bahwa selain karena minat, saya juga punya bakat mengolah si kulit bundar.
“Pap, tadi dhank Ari bikin 3 gol lho!”
“Pap, main bola yuk!”
Tapi sunyi. Harapan itu akhirnya kembali menipis setiap kali malam datang. Saya hanya bisa mencipta banyak mimpi sebagai pelampiasan sedih, sesaat sebelum tidur.
Harapan semakin menipis saja saat sepupu saya, A Beben, yang tinggal di rumah sempat dimarahi habis-habisan oleh Bapak dan Ibu. Alasannya karena A Beben terlalu serius bermain bola di klubnya daripada kuliah. A Beben sempat bersikeras untuk serius bermain bola dan menjadi pemain bola profesional. Apalagi, setahu saya, A Beben awalnya memang ingin kuliah di Fakultas Olahraga dan bukan di Fakultas Sosial dengan jurusan Dunia Usaha. Namun, keinginan itu dengan cepat dipatahkan Bapak dan Ibu, meski saya tak tahu persis atas alasan apa. Somehow, saya mungkin bisa merasakan kesedihan A Beben.
Saya lantas menjadi ciut. Saya pun tak lagi menunjukkan terang-terangan minat saya terhadap sepakbola pada Bapak dan Ibu, termasuk menonton pertandingan sepakbola secara langsung di stadion.
Di sisi lain, saya punya ketakutan.
Saya takut menangis jika menyaksikan sepakbola secara langsung, saking inginnya saya menjadi salah satu dari 22 pemain yang sedang bersenda gurau di lapangan.
dhank Ari at 6:56 AM
Depok, 12 April 2010Di awal hingga pertengahan tahun 1980-an, saya memiliki rutinitas yang mengasyikan. Hampir setiap pagi, saya mendapati Ali sudah berdiri di depan pintu rumah, siap untuk mengajak saya sekolah. Saya biasanya belum siap untuk pergi. Entah karena susu murni langganan yang belum habis saya minum, atau sepatu yang belum saya ikat. Tapi Ali sabar menunggu. Kadang, Ali akhirnya juga ikut menyantap gemblong atau bala-bala, yang Ibu beli sangat pagi pada penjual makanan kecil yang lewat depan rumah.
Lantas, saya dan Ali pun melenggang menuju sekolah. Banyak hal asyik yang kami lakukan sepanjang jalan. Tak pernah bosan. Mulai dari bernyanyi, berjalan bak seorang prajurit, balapan lari, bertingkah layaknya seseorang yang sedang mengemudikan mobil, berjalan mundur sampai melempar batu ke kawasan PLN yang penuh dengan menara listrik, yang kami lewati. Saya dan Ali selalu takut menyentuh pagar kawat yang membatasi kawasan PLN itu dengan setapak yang kami lewati, karena ada sebuah tulisan peringatan yang berbunyi “Awas! Tegangan Tinggi”.
Semuanya sungguh mengasyikan. Saya bahkan pernah terpaksa pulang kembali ke rumah untuk mengganti baju sekolah karena saya terperosok ke dalam sawah, setelah sebelumnya saya justru yang hendak berbuat iseng dengan mendorong Ali ke dalam sawah.
Pulang sekolah, jauh lebih mengasyikan lagi. Saya dan Ali punya sahabat lain di sekolah. Namanya Hendra atau Kuncung. Kita bertiga selalu pulang bersama. Banyak pula hal mengasyikan sepanjang perjalanan pulang. Apalagi, setelah menginjak kelas 3, saya dan Ali tak langsung pulang ke rumah. Kami selalu menyempatkan diri mampir dan bermain di rumah Kuncung, yang memang terletak di jalur pulang kami. Alasan lainnya, adalah karena Kuncung punya lebih banyak mainan dan bacaan daripada kami, termasuk mainan-mainan mahal yang tak sanggup kami beli.
Agenda rutin kami biasanya adalah membaca majalah Ananda dan Kuncung (inilah awal kami memanggil Hendra dengan panggilan Kuncung), bermain Atari, adu gambar, adu kelereng dan menancap mobil kayuh milik Kuncung di sebuah gang sempit. Saya dan Ali biasanya baru pamit jika sore sudah menjelang, dengan sebuah harapan jika esok kami akan bermain lebih asyik lagi.
Jadilah kami Rilicung, alias Ari Ali Kuncung, lewat sebuah konvensi khas anak-anak. Jadilah kemudian kami bersahabat, hingga sebuah institusi sekolah bernama SMP menjauhkan kami semua. Tak ingin, sebenarnya berjauhan, tapi sungguh sulit bermain bersama lagi setelah itu.
Hingga sekarang.
Namun, saya jadi punya harapan. Harapan untuk bisa membangkitkan kembali Rilicung dan maju sebagai Partai Politik yang hanya beranggotakan tiga orang saja. Saya, Ali dan Hendra alias Kuncung.
dhank Ari at 6:52 AM
Tuesday, September 08, 2009
Cuatan kecil...Pernah memandang langit dari sudut matamu. Ternyata buram, tak sejernih kukira. Apa mungkin kau bukanlah pasangan jiwaku?
dhank Ari at 3:53 AM
Cuatan terbaru lagi....seluruhnya resah. Tak terkecuali kata-katamu. Keluar seperti dibalut perban dan berharap waras seperti sedia kali. seluruhnya basah. Tak terkecuali matamu. Menetes deras seraya menjerit meski tanpa pernah tahu kenapa harus kembali terurai.
tertimbun pelataran rasa akan masa lalu, mereka memilih untuk menyisipkan kenangan diantara hiruk kekinian. Tak pernah tahu dimana atau kapan kemudian kerikil itu akan menyandung mereka.
Aku menjejak setapak yg tak berujung. Namun langkah terus ada, meski satu demi satu. Mungkin melarikan kekosongan lebih baik dr sekedar diam.
Rambut itu kau larikan kesana kemari. Menengahi lincah langkah kecilmu. Menengahi juga pandangku yg terus menempel pada energimu.
Kau boleh simpan seluruh rasa lantas kau sembunyikan. Aku tak peduli. Kau pikir aku tak punya sisa? Kau justru hanya mencicipi secuil saja. Tak sampai habis jari.
Tempuhi jejaring asmara bersama rindu yg tak tuntas telah buat kau menghilang sesekali. Aku tak mau sepintasmu. Jadi tuntaskanlah rindu itu sebelum kau lendotkan nirwanamu padaku.
Lintas sejenak pada sebuah ingatan akan angin. Sepanjang sore keparat itu, tak ada hentinya aku merasa hangat karena bisikanmu bersama angin. Andai kutahu jika bisikanmu itu hanyalah rekaman palsu sementara kau merajut rasa yg lain, maka kututupi saja mukaku dgn perisai atau balik menghembus.
Keruh sangat keintimanku dgn Tuhan, hingga meluas jauh di tujuh samudra. Kisruh obrolan jiwa di beberapa purnama, menegaskan bahwa roh penyelamat benar2 dinanti.
Bukan semata mencari kawan dalam gelap. Aku hanya menelusur jalan menuju cahaya. Bukan semata menghibur hitam jiwa yg kusam. Aku hanya mencoba mendekat dgn menjauh.
Untuk mencari, tak banyak tenaga tersisa. Padahal, nafas tinggal satu dua. Waras jiwa pun tinggal menunggu gelap. Biasanya, pengembara peneman angin kemudian datang dengan hembusan dahsyat penumbuh semangat. Tapi, kenapa detik itu terus melaju sementara kau belum juga datang?
ketika rindu ingin bertengger lama di pucuk jiwa, benturan konyol kerap datang dan menipiskan kegembiraan, keriaan dari sebuah keinginan bertemu. Rindu memang seringkali datang dengan berbagai duri, mengantongi sembilu. Berharap saja tak terlupa kewa...rasan hingga akhirnya tersayat karena kebodohan sendiri.
tercium mentari. Tersudut terus di pojokan teduh tak menutupi jejak yang tak ingin terganggu. Betapa cahaya kemudian kembali mendorongku terus dari belakang, menorehkan banyak sekali bayangan. Aku pun harus maju, menemukan bayangan yang tepat.
dhank Ari at 3:51 AM