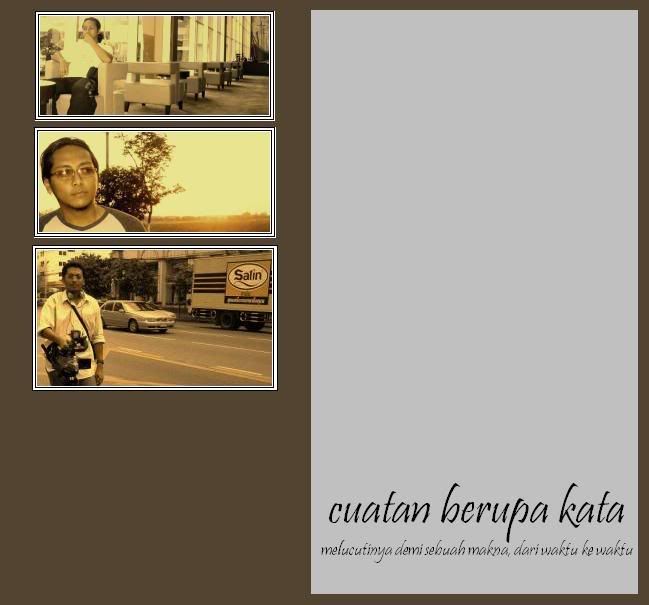Monday, August 09, 2010
Jakarta, 29 Mei 2010Hari Minggu lalu, seperti biasa, saya cuci mobil di Bulletz Car Wash, Radar AURI, Depok.
Seperti biasa pula, saya memesan segelas kopi hitam panas (atau kadang segelas susu putih panas) di warung kopi sebelah Bulletz dan menunggu.
Jika beruntung, saya akan mendapat teman bicara. Tapi seringnya, saya duduk sendiri, sambil sesekali beranjak dan mengintip ke ruang sebelah.
Hari Minggu lalu, adalah salah satu hari beruntung saya. Saat saya masuk ke warung kopi, seorang lelaki, mungkin baru menginjak usia awal 20-an, sudah duduk lebih dulu di sana.
“Istirahat, Mas?”
Saya mencoba praktek deduksi, untuk kesekian kalinya. Satu gerobak tukang loak terparkir mesra di dekat tiang listrik, tak jauh dari warung kopi. Jadi saya pikir, lelaki ini mungkin adalah pemiliknya.
“Iya, Mas.”
“Abis keliling dari mana?”
“Ah, saya sih nyelusurin jalan besar aja, Mas.”
“Oh, gitu? Gak masuk ke perumahan?”
“Jarang, Mas. Paling sering, saya masuk ke bengkel-bengkel atau kantoran aja, Mas.”
“Hm...Kenapa begitu?”
Obrolan terus berlanjut, bahkan ketika pesanan indomie rebusnya datang, sampai akhirnya saya melontarkan tawaran.
“Suka dapet perangko gak, Mas?”
“Perangko?”
“Iya. Perangko. Itu lho yang biasanya ada di amplop surat. Yang suka ada harganya. Bisa 500 perak, bisa seribu atau berapa aja lah.”
“Oh, yang warnanya suka ijo atau merah gitu, ya?”
Saya sempat ingin terdiam dan berpikir sebentar. Apa benar lelaki ini, yang belakangan saya tahu namanya adalah Mardianto, tidak tahu perangko? Apa ia tidak pernah melihat perangko seumur hidupnya?
Tapi diam itu urung saya lakukan. Biarlah saya akan diam berpikir nanti, setelah obrolan kami usai. Dan kami pun terus berbincang, sampai akhirnya ia pamit dan mulai keliling lagi.
Sepanjang perjalanan pulang ke rumah setelah itu, pikiran saya terisi terus oleh perangko dan Mardianto.
Saya pernah punya romantisme tentang perangko.
Ketika teknologi informasi tak semaju sekarang, salah satu cara saya dalam berkomunikasi adalah lewat surat, yang sebagian besar tak lepas dari keberadaan perangko. Saya dulu sering tertawa kecil saat mengambil setumpuk surat dari tukang pos dan menyerahkannya pada Papap atau Mamah. Kasihan Suharto, sang presiden. Wajahnya kerap dipukuli dan dikotori oleh stempel. Kadang sampai membuat mukanya jelek tak keruan karena permukaan perangko itu tertekan cukup keras oleh stempel atau bahkan jadi seperti badut dengan perona muka warna hitam yang terlalu banyak.
Apa sedemikian asingnya perangko bagi sebagian orang saat ini? Mungkin juga pada anak-anak usia muda?
Ingin bertukar kabar, tinggal buka jejaring sosial seperti facebook atau twitter dan ngobrol secara tidak nyata sepuasnya. Chatting, kalau bahasa kerennya.
Atau mungkin lewat layanan pesan singkat di telepon seluler yang isinya bisa sampai saat itu juga pada orang yang dituju. Tanpa jeda seperti surat, apalagi surat dengan perangko biasa, yang bisa sampai berhari-hari di tempat tujuan.
Atau juga lewat perbincangan panjang lebar di telepon seluler yang tarifnya makin murah saja sekarang.
Kalaupun ingin mengirimkan kabar yang lebih resmi atau lebih panjang atau atas alasan apapun juga, masih ada fasilitas surat elektronik atau email.
Apa orang masih berkirim surat secara konvensional?
Di rumah saya sekarang (atau juga di kantor), surat yang datang tak pernah beragam lagi dan mengandung unsur kejutan. Selalu saja surat-surat itu tak lepas dari surat tagihan kartu kredit, indovision, PAM, asuransi dan lain-lain.
Jika dulu, surat yang datang menagih kabar dari saya sambil berbagi cerita dari seberang sana. Kini, surat yang datang menagih uang dari saya sambil berbagi produk konsumerisme yang terus mereka cekoki untuk saya beli.
Jika dulu, tukang pos datang disambut dengan gairah untuk mendapatkan kejutan dan juga perangko yang mungkin tak sama dengan perangko pada surat sebelumnya. Kini, tukang pos datang disambut dengan dingin bahkan sedikit membuat kening mengkerut dan tak ada lagi kejutan perangko melainkan stempel perangko berlangganan yang membosankan.
Lantas di sisi lain, masih adakah sosok-sosok seperti Suharto yang rela narsis meski harus dikotori stempel?
Saya akhirnya lupa pada maksud awal dari tawaran saya pada Mardianto. Saya hanya ingat romantisme masa lalu, saat saya masih getol koleksi perangko, sampai kadang harus menjemur perangko yang sudah dilepaskan dari amplopnya itu berjejer di sekujur kaca nako ruang tamu.
dhank Ari at 7:22 AM