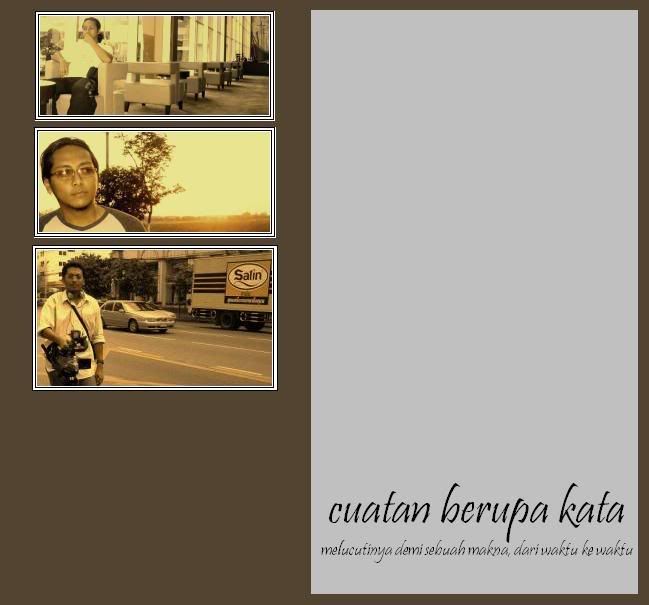Monday, September 18, 2006
Selisih 500 peraktapi penting untuk hatiAwal tahun 1999, aku lulus kuliah. Meski nilainya tak terlalu bagus, aku tetap bersyukur karena pada akhirnya, ada sesuatu yang tuntas dalam hidup, meski belum sepenuhnya tuntas karena perjuangan yang anyar sebenarnya akan segera dimulai, lagi.
Mengamini sebuah pemikiran seorang filsuf bahwa tak pernah ada yang tuntas dalam kehidupan, kecuali kematian.
Setelah kelegaan perasaan atas kelulusan itu membawa aku pada kelengahan, aku pun mulai ditembak oleh sebuah peringatan keras. Di akhir bulan yang sama dengan bulan kelulusan, aku menyadari bahwa tak ada lagi uang tersisa di kantong, bahkan di dalam catatan rekening di Bank. Semuanya habis untuk biaya kelulusan, dan mengongkosi orang tua dari kampung.
Sial!!
Aku sempat memaki dalam hati, mengutuki nasib karena tak bisa menikmati sebentar saja euforia kebahagiaan dan harus kembali pada penat penyelamatan diri di kota besar seperti Jakarta. AKu tahu persis bahwa tak ada yang gratis di sini. Semuanya dihargai dengan uang, yang mau tak mau harus kukejar tanpa berpikir untuk rehat barang sejenak saja.
Aku putar nomor-nomor itu lagi, sambil menyatakan aku sudah kembali dari cuti panjangku. Hampir sebulan lebih, aku tidak mengajar anak-anak itu dan kini aku harus kembali. Beberapa dari mereka menyanggupi namun beberapa dari mereka ternyata sudah memutuskan untuk tidak menyewaku lagi sebagai pengajar mereka. Pengorbanan! Kehilangan penghasilan! Tapi aku tak menyalahkan mereka karena mereka toh butuh seseorang untuk membimbing mereka dalam pelajaran yang mungkin sekali tak bisa ditinggal cuti seperti yang telah aku lakukan terhadap mereka.
Keesokan harinya, aku sudah siap kembali mengajar. Hasil mengajar bulan ini akan aku tabung untuk membeli banyak sekali amplop coklat seukuran kertas polio, untuk menyewa komputer berjam-jam di rental dan cetak foto, juga sebanyak-banyaknya. Maklum, aku sudah siap melamar kerja dengan status sebagai sarjana.
Kemudian, kebimbangan itu muncul juga pada akhirnya.
Saat kondektur bis Depok-Pasar Minggu menelorkan teror bunyi kecrekan koin itu di depan mukaku, aku terdiam sebentar dan berpikir.
“Berapakah yang harus saya kasih ke dia? Dua ratus perak ataukah tujuh ratus perak?”
Aku sadar bahwa statusku sekarang bukan lagi mahasiswa. Aku sudah lulus dan statusku kini adalah pengangguran. Tak ada harga istimewa bagi seorang pengangguran saat membayar ongkos bis. Sama seperti penumpang pada umumnya, tujuh ratus perak.
Tapi, aku sedang tak punya uang dan butuh sekali menabung untuk melamar kerja. Apa aku akan memposisikan diri sebagai mahasiswa, apalagi mengingat aku baru saja lulus sehingga tak akan terlalu berpengaruh, baik bagi rasa bersalahku maupun bagi kondektur itu?
Kondektur itu kembali menelorkan teror recehan itu dan seakan mulai kehilangan kesabarannya.
Aku pun memutuskan untuk membayarnya tujuh ratus perak.
Sebenarnya, aku bisa saja memposisikan diri sebagai mahasiswa, baik secara penampilan maupun secara pembubuhan pada batinku. Tapi aku tahu, bahwa hal itu akan berpengaruh besar pada kejujuranku. Jadi aku lebih baik mencatatkan dalam buku harianku hari ini bahwa ongkos untuk mengajar ke tempat Ayu di Jalan Benda tidak lagi 800 perak pulang pergi, melainkan 2800 perak pulang pergi. Yang artinya, penghasilanku akan berkurang sebanyak 2000 perak, hingga aku harus berusaha lebih keras lagi atau mencari sumber pendapatan yang baru.
Bukanlah hal yang menyulitkan, menurutku, karena konsekuensi sebuah kejujuran selalu dapat diterima hatiku dengan baik dan menimbulkan ketenangan luar biasa meski harus menuturkan terus peluh-peluh itu tanpa henti. Kejujuran untuk diperjuangkan, bukan semata didengungkan.
dhank Ari at 5:13 AM